
Cerpen Perlawanan; Saripah dan Istri-istri Nelayan
Cerpen Perlawanan; Saripah dan Istri-istri Nelayan
Suara kokok ayam jantan membangunkan bhatara surya dari tidurnya. Dengan gagahnya ia menari menyemburkan sinar merah yang semburat di ufuk timur sana. Gaduh suara ombak menggulung berkejaran menghantam pasir hitam berkilau kuning kemerah-merahan. Seorang wanita paruh baya berdiri mematung menatap samudera dengan sorot mata tajam. Semilir angin membisik lirih membawa kabar akan datangnya pagi. Pagi yang penuh dengan harapan. Entah kepalsuan atau kepastian yang ia tawarkan, yang jelas pagi selalu hadir dengan segudang harapan. Sederhana, wanita itu hanya berharap lelakinya pulang dengan selamat dan jukung (perahu kecil dengan mesin satu atau dua) penuh dengan hasil tangkapan.
Ya, perempuan. Struktur sosial masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan menempatkan kaum perempuan pada posisi dan peranan yang khas sebagai manifestasi dari karakteristik aktivitas ekonomi perikanan tangkap. Posisi sosial yang spesifik ini menjadikan perempuan pesisir (khususnya istri-istri nelayan) memainkan peranan penting dalam menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kedudukan sosial yang demikian diperoleh perempuan pesisir karena tuntutan alamiah, bukan karena hasil dari intervensi kebijakan resmi berdimensi kesetaraan gender.
Masyarakat nelayan adalah masyarakat “tanpa negara”, karena kemampuannya yang tinggi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial ekonomi yang rumit tanpa bantuan negara secara berarti. Namun masyarakat nelayan bukanlah masyarakat “komunal primitif” yang hidup tanpa ada ikatan dengan masyarakat lain. Masyarakat nelayan masih tidak bisa lepas dari para pedagang perantara atau middleman yang dalam masyarakat madura disebut pengamba’ (baca:pengambeq) atau peraih dalam bahasa melayunya. hubungan ini sedikit agak mirip dengan hubungan antara masyarakat feodal dan masyarakat borjuis. Kemiripan itu juga dibuktikan dengan realita bahwa tak semua nelayan bekerja dengan perahunya sendiri. Ada beberapa nelayan yang bekerja untuk orenga (juragan) istilah nelayan madura. Nelayan yang demikian itu disebut pandhiga (nelayan buruh/awak perahu).
Dan perempuanlah yang menjadi penghubung antara keduanya. Laut adalah ranah kerja laki-laki (nelayan) dan darat adalah ranah kerja perempuan pesisir. Kegiatan utama laki-laki adalah menangkap ikan, sedangkan perempuannya mengolah dan menjualkan hasil tangkapan suami. Sebagian besar waktu dihabiskan nelayan untuk menangani pekerjaan melaut, sehingga tidak cukup kesempatan bagi nelayan mengurus aktivitas sosial ekonomi di darat. Sebaliknya, perempuan pesisir menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menangani pekerjaan-pekerjaan di darat. Karakteristik geografis dan mata pencaharian dikawasan pesisir telah membentuk peranan sosial-ekonomi yang khas para nelayan dan istrinya.
Deru ombak semakin gaduh, burung-burung laut menari berputar-putar di atas pasir. Matahari perlahan mulai memanjat langit, sinar terangnya menghajar apapun dan siapapun melahirkan bayang-bayang. Perempuan-perempuan itu, istri-istri nelayan itu, satu demi satu datang dan berkumpul. Mereka sembunyi di dalam gubuk bambu kecil dengan tatap mata penuh harap. Sesekali mereka melempar canda untuk mengusir gelisah. Gelisah yang timbul karena ke khawatiran terhadap keselamatan lelakinya. Wajar, kekhawatiran itu sangatlah wajar. Lelakinya berlayar di laut lepas, mereka berlayar menyusuri Samudera Hindia, bukan laut dangkal di perairan utara jawa.
Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hanya menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Namun ada beberapa masyarakat nelayan lain yang juga menggantungkan hidupnya dari hasil laut dan hasil pertanian meskipun itu hanya sebagai pekerjaan sampingan. Ini biasanya mereka lakukan untuk menyiasiati kebutuhan ekonomi ketika hasil tangkapn sepi atau ketika musim laib (tidak ada ikan). Namun ketika kita berbicara masyarakat pesisir, hal ini menjadi lebih kompleks, karena masyarakat pesisir tidak hanya terdiri dari masyarakat nelayan. Dalam masyarakat pesisir, selain masyarakat nelayan, adapula masyarakat petani dan masyarakat pedagang. Yang masing-masing kelompok masyarakat mempunyai struktur yang berbedara.
Boleh juga kita katakan bahwa, masyarakat nelayan, masyarakat pedagang, dan masyarakat petani adalah sub kultur dari kultur masyarakat pesisir. Meskipun kita tahu bahwa kelompok masyarakat pesisir dan kelompok masyarakat pedagang juga terdapat dalam kultur masyarakat lain. Namun masyarakat petani pesisir dan masyarakat petani pegunungan sangatlah berbeda. Sangat jarang, bahkan hampir tidak ada kita temukan masyarakat petani ansih dalam kultur masyarakat pesisir. Berbanding terbalik, masyarakat petani ansih justru akan lebih banyak kita temukan di masyarakat agraris. Meskipun juga dapat kita jumpai dalam masyarakat agraris kelompok masyarakat yang menempatkan bercocok tanam sebagai mata pencaharian sampingan. Kondisi ini juga sama kita temukan dalam masyarakat pesisir, yang ada beberapa kelompok masyarakat nelayan yang tidak hanya berprofesi sebagai nelayan.
Kusen adalah salah satunya, tidak seperti kebanyakan nelayan ansih yang ketika musib laib mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di darat untuk memperbaiki jala atau perahunya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka terpaksa menjual perkakas rumah atau bahkan meminjam uang ke rentenir. Kusen dan beberapa kelompok masyarakat nelayan ini menutup kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan hasil pertanian. Ketika hasil tangkapan menurun atau ketika cuaca tidak memungkinkan untuk pergi ke laut, bapak dua anak ini masih bisa bekerja dengan menggarap sawahnya. Tidak luas memang, tapi cukup untuk menambal kebutuhan hidupnya sehingga ia tidak sampai terjerat utang kepada lintah darat (rentenir).
Sama dengan petani lainnya, Kusen juga memelihara ternak sebagai cadangan kebutuhan. Konsep ini yang banyak dikenal dikalangan masyarakat petani adalah konsep rojo koyo. Yaitu konsep menabung kekayaan dalam bentuk ternak seperti kerbau, sapi, atau kambing. Ini biasanya dilakukan oleh petani untuk menyiasati ketika datang musim paceklik. Untuk menutup kebutuhan pada masa paceklik itu biasanya para petani menjual ternaknya untuk bertahan hidup.
Sedangkan Saripah istrinya, biasanya akan membantu suaminya untuk mengurus semua pekerjaan suaminya baik ketika di laut maupun di sawah. Pun demikian dengan anak-anaknya, mereka bertanggungjawab atas ternak dengan mencari rumput sepulang sekolah. Pembagian tugas secara kompleks yang melibatkan anggota keluarga inilah yang membedakan masyarakat nelayan dan masyarakat lainnya. Sekilas ada kesamaan dengan pembagian tugas masyarakat petani, namun ada beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Dalam masyarakat nelayan ansih sekalipun, pembagian tugas yang melibatkan seluruh anggota keluarga tetap dilakukan.
Namun yang membedakan masyarakat nelayan ansih dan nelayan lainnya adalah masyarakat nelayan ansih lebih mencirikan masyarakat komunal primitif. Ciri itu terlihat dari kesamaan atas ketidak mampuan mereka untuk memproduksi barang secara mandiri. Ini berbeda dengan nelayan tambak, jelas, nelayan tampak punya kemampuan untuk memproduksi barang secara mandiri. Meskipun jelas ada beda antara masyarakat nelayan ansih dan masyarakat komunal primitif. Masyarakat komunal primitif tidak memiliki ketergantungan terhadap kelompok lain untuk bertahan hidup, sedangkan masyarakat nelayan ansih memiliki ketergantungan yang kuat terhadap middleman atau pedagang perantara. Dalam hal ketergantungan ini sebenarnya masyarakat nelayan ansih ataupun masyarakat nelayan lain sama dengan hubungan antara masyrakat feodal dan masyarakat borjuis. Bahkan bisa dikategorikan masyarakat nelayan adalah bagian dari masyarakat feodal. Karena ada beberapa kelompok nelayan pandhiga (nelayan buruh/awak perahu) yang bekerja untuk tuan-tuan mereka (pemilik perahu). Hal ini sama dengan tatanan masyarakat petani (buruh tani) yang bekerja untuk tuan-tuan tanah.
Suara gemuruh ombak berpacu dengan suara bising mesin medorong jukung-jukung nelayan berpacu menyium bibir pantai yang indah dengan pasir hitam berkilauan. Para perempuan itu berdiri dan segera menjemput lelakinya pulang dari berperang menakhlukan ganasnya samudera. Para pengamba’ dan beberapa juragan juga ikut menyamput pahlawan penakhluk samudra itu dengan penuh antusias. Mereka, istri-istri nelayan, juragan kapal, dari para pengamba’ punya harapan yang sama. Harapan yang selalu yang ditawarkan oleh pagi dengan sinar indah mentari yang merah merekah. Harapan bahwa hasil tangkapan hari ini cukup bagus sehingga dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah.
Namun terkadang harapan tak sesuai kenyataan. Hari ini hasil tangkapan tak begitu banyak. Mentari tak seindah tadi pagi, sinarnya tak lagi sejuk. Kini ia mulai meninggi, pantaslah pula bila kulit terasa panas disengatnya. Tapi sedikit apapun hasil tangkapan itu, tetap saja akan menjadi rupiah. Entah cukup atau tidak untuk menambal biaya oprasional, ikan-ikan hasil tangkapan tetap harus jadi rupiah. Paling tidak, setelah mentari tenggelam nanti, cukup untuk menghadirkan sepiring nasi dimeja makan. Dan yakin, esok akan datang lagi pagi. Pagi yang tawarkan semangat baru, semangat untuk hidup, semangat untuk bercumbu dengan samudera, karena rejeki mereka ada disana.
Burung-burung laut sesekali juga bergabung untuk berbagi kecerian. Berbaur dengan hiruk pikuk satu-persatu jukung nelayan yang pulang membawa hasil tangkapan. Persis seperti mereka, yang mengais rejeki di tepian. Mencengkeram pasir, bergumul ombak, dan menari dengan angin yang membawa kabar dari lautan.
Dari jauh aku memandang, dari bawah pandan laut yang rindang. Aku terkagum meliahat pemandangan itu. Tak ada lain, yang membuatku kagum adalah perempuan-perempuan itu. Mereka mengingatkanku pada perkataan Lily Braun, seorang tokoh pemimpin perempuan. Ia mengatakan bawa, “Perempuan pada abad ke-19 hingga ke-20 itu nasibnya sama dengan keledai kecil yang musti manarik dua kereta, yaitu kereta rumah tangga dan pekerjaan (mencari nafkah)”.
Wanita boleh modern, boleh “feminis”, boleh menjadi orang yang berpangkat tinggi, atau kuli hina-dina yang membanting tulang lima belas jam sehari di pabrik, tetapi ia tetap wanita, yang ingin cinta, yang ingin kasih, yang ingin membahagiakan suami dan anak. Meskipun badan telah letih dan hampir remuk, pinggang telah patah karena kecapean, setiba di rumah setelah dari pabrik, kebun, atau mungkin dari pesisir (istri nelayan), ia akan bekerja lagi, ia akan memeras keringat lagi,untuk suami dan untuk buah hatinya. Ia tidak akan dapat melepaskan diri dari tarikan jiwa itu.
Orang Inggris mempunyai syair yang bunyinya, “Man works from the rise to set of sun. Women’s works is never done”. Yang artinya kurang lebih demikian, “Laki-laki bekerja dari matahari terbit sampai terbenam, sedangan perempuan bekerja tiada hentinya siang dan malam”.
Syair itu tidaklah berlebihan, karena pada faktanya perempuan harusa terus bekerja keras siang dan malam. Setelah harus membanting tulang mengais rupiah, mereka harus juga disibukkan dengan urusan-urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu dll. Bahkan tengah malam sekalipun terkadang mereka harus terbangun untuk menjalankan kewajiban seorang istri melayani suaminya. Begitulah potret wanita masyarakat kelas bawah, mereka seperti mesin yang seolah tak pernah kenal lelah. Namun yang demikian itu jarang kita temui dalam wanita masyarakat kelas menengah atau kelas atas.
Janganlah lelaki mengira, bahwa bisa ditanam suatu kultur yang sewajar-wajarnya kultur, kalau perempuan dihinakan di dalam kultur itu. Setengah ahli tarich (baca:tareh) atau sejarah mengatakan bahwa kultur yunani jatuh karena perempuan dihinakan dalam kultur yunani itu. Dan semenjak kultur masyarakat islam (bukan agama islam) kurang menempatkan kaum perempuan perempuan pada tempat yang seharusnya, maka sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, matahari kultur masyarakat islam mulai tenggelam.
Beratus-ratus tahun sebelum di Eropa ada maha-maha guru seperti Maxwell, Pharaday,Nicola Tesla, Descartes, Hegel, Spencer, atau William Thompson, di padang pasir yang tandus seorang yang tak pernah mengenal baca tulis bernama Muhammad SAW pernah bersabda, “perempuan adalah tiang negara. Apabila baik perempuannya, maka baiklah negara itu. Apabila rusak perempuannya, maka rusaklah perempuan itu”.
Namun menjadi masalah ketika itu dimaknai secara dangkal. Banyak lelaki karena tak ingin melihat perempuannya rusak, dikurungnya perempuannya, dikerangkengnya, dikekangnya, di batasi semua aksesnya. Bahkan para suami dengan dalih mencintai istrinya, kebablasan dalam memuja. Banyak laki-laki yang menghargakan istrinya seperti mutiara. Mereka memuliakan istri mereka, mencintainya seperti barang berharga, mereka pundi-pundikannya sebagai mutiara, tetapi justru sebagian orang menyimpan mutiaranya di dalam kotak, Demikian pulalah mereka menyimpan istrinya dalam kamar atau pingitan.
Dalam hal ini laki-laki menempatkan perempuan sebagai blasteran (percampuran) antara seorang Dewi dan seorang tolol. Dipundi-pundinya, dipuja-pujanya sebagai seorang dewi, namun di satu sisi ia membatasi semua ruang gerak perempuan, perempuan di cap sebagai makhluk yang tak akan bisa hidup sendiri. Mereka terlalu lemah untuk mengerjakan urusan-urusan masyarakat, perempuan di dakwa tak pantas untuk mengerjakan apapun diluar rumah, perempuan tidak akan becus mengerjakan urusan lelaki, bukankah ini sama dengan men-tolol-kannya?. Lebih terlihat tolol lagi ketika kita melihat perempuan hanya dijadikan pajangan. Mereka, para nonik dan putri-putri raja ini hanya boleh tenguk-tenguk, duduk di bawah jendela. Bahkan secara ekstrim laki-laki mengatakan bahwa tugas perempuan hanyalah masak, macak, manak (memasak, bersolek, dan melahirkan).
Jeltse de Bosch Kemper, seorang perempuan belanda mengeluhkan hal yang demikian itu, “Apa yang saya kerjakan dari umur delapan belas tahun, saya tidak tahu. Saya tinggal dirumah saja, menyulam, menggambar, main piano, menjahit, dan jalan-jalan. Kadang banyak juga hasil pekerjaan itu, tetapi terlalu banyak yang sia-sia”. Adakah keadaan dikalangan perempuan atas Indonesia berbeda? Siapa yang membaca karya R. A. Kartini akan mendapati hal yang sama. Mendadak, para perempuan ini berupah menjadi mesin ngomong yang kritis dengan keluhan-keluhan yang menumpuk hingga segudang.
Sepintas putri-putri itu nampak lebih mulia dari emban-nya (perempuan pengasuh), sepintas saja terlihat seperti itu. Tapi coba kita lihat dengan lebih jernih, putri-putri itu nampak seperti robot, kalau tidak mau saya katakan seperti hewan ternak. Bagaimana tidak, bangun pagi, sarapan, masuk kamar lagi, kadang bermain sebentar, ketika malam tiba mereka harus masuk kamar lagi, makan malam, tidur, begitu setiap harinya. Bahkan mereka lebih tertindas dari pada buruh sekalipun, fisiknya tidak, tapi hatinya sangat, bahkan teramat sangat tertindas. Dalam masyarakat modern seperti hari ini-pun, gadis-gadis masih harus dibatasi ruang geraknya. Mereka tak ubahnya tahanan kota, yang selalu di awasi gerak-geraknya, dan boleh bepergian jauh atas ijin orang tua mereka.
Maka berbondong-bondong kaum perempuan dalam melakukan pemberontakan. Mereka robohkan dinding tabu itu, mereka menolak disebut Dewi-Tolol. Mereka bergerak, menyusun kekuatan untuk merobohkan dominasi laki-laki. Ini kemudian yang kita kenal dengan istilah emansipasi wanita. Gerakan untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Atas nama Hak Asasi Manusia (HAM), atas nama kesetaraan gander. Namun mereka lupa, bahwa orang lain juga punya Hak Asasi, lelaki juga punya Hak atas istri dan anak punya Hak atas Ibu.
Hari ini Aku melihat perempuan-perempuan itu, istri-istri nelayan itu, lebih modern, lebih feminisme dari perempuan-perempuan borjuis kota, bahkan dari aktifis gander sekalipun. Mereka jauh menyelami apa yang oleh para ahli atau oleh para aktifis perempuan disebut dengan kesetaraan gander. Perempuan-perempuan itu, istri-istri nelayan itu, telah jauh secara teoritis untuk menjelaskan apa itu feminisme, apa itu kesetaraan gander dalam prakteknya sehari-hari.
Mereka berdiri sama tinggi dengan lelakinya dalam hal menopang ekonomi keluarga. Namun tak seorangpun aktifis perempuan yang berani mengkatagorikan istri-istri nelayan itu dalam teorinya sebagai wanita karir. Tidak, tidak ada, atau lebih tepatnya belum ada. Atau sudah ada, tapi malu-malu mengakuinya. Bahkan seharusnya mereka, masyarakat modern itu, wanita karir itu, aktifis feminisme itu, belajar kepada perempuan-perempuan istri nelayan. Apa yang dipelajari? Belajar menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya dan istri yang baik untuk suaminya. Diluar itu, soal karir, soal pekerjaan, soal ekonomi, silakan menggurui mereka. Tapi untuk dua hal ini, menjadi istri dan ibu yang baik, sudah seharusnya mereka belajar dari perempuan-perempuan istri nelayan itu.
Ini adalah potret Sarinah, seorang sosok perempuan tangguh yang dilukiskan Ir.Sukarno enampuluh sembilan tahun silam dalam bukunya yang berjudul Sarinah, “kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia”. Dalam era kemerdekaan ini, Aku melihat semangat itu dalam sosok perempuan-perempuan Muslimat Nahdlatul Ulama dan Aisiyah Muhammadiyah. Perempuan-perempuan progresif yang tidak pernah melupakan tugasnya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya dan sebagai seorang istri dari suaminya. Meskipun jarang sekali mereka menggembar-gemborkan diri sebagai aktifis gander dan aktifis feminisme. Sama dengan perempuan-perempuan istri nelayan itu, bahkan mereka tak tahu dan tak mengenal apa itu gander dan feminisme.
Jauh sebelum perempuan-perumpuan itu menuntut atas hak-nya, menuntut kebebasanya, seorang buta huruf dari padang pasir yang bernama Muhammad bin Abdullah, seorang yang kemudian terpilih sebagai utusan Allah untuk membawa misi kemanusiaan, membawa agama Tuhan, telah memperjuangkan nasib perempuan. Seorang laki-laki memperjuangkan hak-hak dasar perempuan, bukan perempuan yang memperjuangkan perempuan. Tapi seorang laki-laki yang memperjuangkan hak perempuan, jauh sebelum kaum perempuan memperjuangkan hak-nya sendiri. Seperti kita ketahu dari cerita-cerita sejarah, pada masa Jahiliyah atau masa kebodohan, masyarakat Arab Quraisy menyembelih atau mengkubur hidup-hidup setiap bayi perempuan. Karena dianggapnya perempuan tidak berguna, hanya akan menghabiskan harta saja. Tidak dapat di ajak berperang, tidak bisa melindungi diri, dan tidak bisa diajak berdagang. Maka, mempunyai anak perempuan adalah aib bagi seorang Arab Quraisy.
Matahari semakin meninggi, bathara bayu menggiring angin semilir menelusup sela-sela dedaunan rindang di tepi pantai. Nyiur melambai-lambai memanggil-manggil ombak yang dibalas dengan gemuruh menggelegar bersahutan, menggulung dan berlari berkejaran berlomba ketepian.
Aku menghela nafas panjang, kuhisap dalam sebatang rokok itu. Asap putihnya aku semburkan dari mulut dan lubang hidungku. Aku mendengar kalau pesisir pantai itu mau ditambang. Aku tak sanggup membayangkan andai tambang benar-benar terjadi.
“Saya lebih memilih hidup seperti ini mas, setidaknya kami tidak menjadi budak di negeri sendiri. Sawah nggarap sendiri, perahu punya sendiri, dan itu lebih dari cukup. Kami tidak menjamin kalau nanti pasir ini akan jadi ditambang, keadaan ekonomi kami akan membaik”, celetuk Bu Saripah.
Dengan menepuk pundaknya aku berkata, “yang mau nambang itu siapa to Bu…..???”, candaku.
“Yo ora weruh aku mas, pokoknya jangan sampai ada tambang disini, kalau ngengkel biar kami, para ibu-ibu yang maju”, omelnya
Dengan nada sedikit ketus Pak Kusen menyela, “Halah….koyo wani-wanio”. Akupun tertawa mendengar perdebatan suami istri ini.
“Yo wani to, siapa yang takut. Jangan dikira kami kaum perempuan tidak punya keberanian. Lihat itu di tipi (TV), bagaimana ibu-ibu kendeng menghentikan tambang semen di Remnbang. Wong lanang kok senengane ngremehne wong wadon”, Bu Saripah terus saja mengomel. Kami berdua memilih diam dan mendengarkan semua celotehnya, karena kalau kami sampai menjawab, bisa-bisa urusan bakal panjang.
“Kalau ini ini ditambang, terus kita makan apa?, Gunung pasir dihancurkan, dikeruk, terus ape nandur opo? (mau menanam apa). Terus jukung-jukung itu mau sandar dimana? Petani makan apa? Nelayan makan apa? Kalau mata pencahariannya dimatikan. Semakin jauh dari janji kesejahteraan yang mereka tawarkan, justru itu akan menggiring kita kejurang kemiskinan”, omel Bu Saripah sambil tangannya menuding-nuding.
Memang, beberapa masyarakat nelayan menyandarkan kapalnya atau jukung-nya diwilayah pesisir. Ini biasanya dilakukan masyarakat nelayan yang tidak punya muara. Untuk masyarakat yang wilayahnya punya muara maka jukung dan kapalnya bersandar di muara atau masyarakat nelayan jawa mernyebutnya pancer.
Semakin teranglah aku menilai perempuan pesisir. Mereka bukan budak seks yang hanya bertugas melayani suami. Mereka merdeka secara utuh, mereka adalah aktifis gander seseungguhnya, perempuan modern sesungguhnya, feminisme sesungguhnya, meskipun mereka tak terlembagakan dan dan paham dengan teroi-teori tetek-mbengek yang justru jauh dari praksis.
Banyak lelaki salah menilai perempuan. Dikiranya perempuan itu adalah budak saja, tempat membuang benih saja, tempat bermain-main saja. Bahkan banyak pula yang menganggap Tali-sekse, sahwat, hubungan seksual sebagai suatu keperluan tubuh saja, sebagai misalnya tubuh perlu kepada air segelas kalau tubuh itu dahaga. “teori air segelas” ini pada awalnya sangat laku dikalangan pemuda-pemuda Rusia. Madame Kollontay menjadi salah seorang penganjurnya. “Siapa merasa dahaga seksual, ia ambil air segelas itu, habis minum, sudahlah pula”. Beberapa tahun lamanya teroi air segelas ini sangat laku. Tapi kemudian…. kodrat alam bicara. Kodrat alam tak puas hanya dengan air segelas saja, kodrat alam minta pula minuman jiwa. Kodrat alam meminta cinta yang lebih meuaskan cita, cinta yang lebih tinggi. Namun teori itu belum sepenuhnya musnah, hari ini teori itu menjadi dasar hukum persundalan atau pelacuran. Belum ada yang menghajar hingga runtuh teori itu, bahkan kelas menengah sekalipun masih banyak yang menggunakan teori itu sebagai dasar hukum seks bebas, kumpul kebo, dan hubungan tanpa status yang lagi ngetren di kalangan masyarakat kelas menengah, terutama pemudanya itu.
Perempuan kembali terhina, masyarakat modern hari ini kembali ke zaman primitif secara akhlak dan moral. Sama seperti zaman Jahihiliyah, maju secara ilmu pengetahuan dan ekonomi, namun bobrok dalam hal moralitas. Benar kata Bung Karno, sang proklamator itu mengatakan dalam salah satu pidatonya, “Bahwa tahap pertama dan paling utama untuk mengawali pembangunan di Republik ini adalah membangun jiwa bangsa”. Ini yang oleh Wage Rudolf Supratman di tulis dalam syair lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”. Mari kita bangun mental kita, mari kita bangun, moral kita, mari kita bangun, akhlak kita, sebelum kita membangun fisik kita, sebelum kita membangun insfratuktur kita, sebelum membangun ekonomi bangsa.
Terutama mental, moral, dan spiritual perempuan-perempuan Indonesia. Karena kelak mereka akan mengajarkan dan meneruskan ini kepada anak-anaknya. Perempuan adalah tiang negara, maka harus kita jaga. Jangan sampai roboh tiang itu, jangan sampai ambruk mental dan moral para ibu. Apabila perempuan telah hancur, mental dan moral para ibu telah rusak, maka rusaklah generasi penerus kita. Itu secara otomatis robohlah negara ini dengan sendirinya..
Maka tepatlah kata Saripah yang istri nelayan itu, kita harus menjadi raja dirumah sendiri. Jangan pernah mau menjadi budak di negri sendiri. Mental perempuan seperti Saripah inilah yang harus kita tanamkan pada generasi penerus bangsa. Perempuan adalah penentu sejarah. Perempuan yang akan melahirkan generasi penerus bangsa. Negara kita negara agraris, mari kita perkuat ketahanan pangan kita. Negara kita negara maritim, mari kita tingkatkan hasil laut kita. Menanam untuk melawan, daripada menambang, lebih baik mencari ikan.
“Waduh grimis mas, monggo pinarak teng ngriyo mawon, istirahat dirumah saja mas”, Celetuk Bu Saripah dengan kepala dan tangan menengadah kelangit.
Tanpa basa-basi aku langsung menyaut, “Monggo-monggo”.
Kamipun berkemas untuk pergi meninggalkan gubuk bambu itu. Meninggalkan bekas semangat perlawanan yang terlukis di atas pasair hitam mengkilat beraromakan titanium. Aroma yang mengundang anjing-anjing kapital untuk datang dan menjajah petani dan nelayan Paseban. Saripah, dan istri-istri nelayan lainnya telah bertekad untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Menghilangkan segala jenis penindasan, menghapuskan segala jenis perbudakan, dan meniadakan penghisapan kaum kapital. Saripah meninggalkan gubuk perlawanan yang kini di guyur hujan. Hujan yang akan menumbuhkan tunas-tunas baru, tunas-tunas perlawanan.
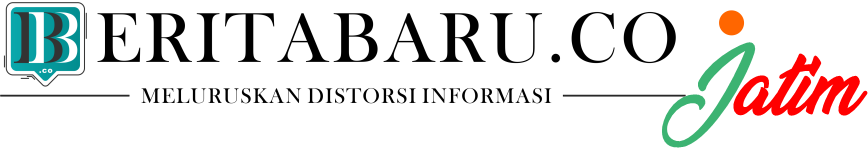
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co







