
Balada Kota Tua | Cerpen: Dinda Agustin A.P.
Duhai Nona yang pipinya merona, coba buang pandanganmu ke sisi barat. Akan kau temukan pipi sang baskara mulai kemerahan, malu-malu dipeluk khatulistiwa. Padahal sang rembulan sudah merajuk. Tak sabar ingin segera merebut perhatianmu. Sayang seribu sayang, nyatanya mataku sudah mendapatkannya terlebih dahulu.
Tatapanmu seakan enggan lepas dariku. Entah apa yang kau pikirkan, hanya kau yang tahu. Namun, aku merasakan kehangatan itu, merangsek jauh ke dalam hati yang beku. Mencairkannya perlahan hingga menetes peluhku.
***
Samar-samar sorot mercusuar memancar. Sesaat lagi akan kucium wangi daratan setelah berbulan-bulan berkelana menyusuri samudera. Mengantar berbagai macam manusia dengan segala kepentingannya.
Bukankah rasa bosanku manusiawi? Jika yang mampu menghiburku hanya segerombolan ikan yang berenang bersamaan. Timpang sekali dengan daratan yang menyuguhkan berbagai kesenangan. Tak heran, anak buahku bermetamorfosis dari ikan tuna menjadi piranha yang beringas saat mencium aroma daratan.
Heboh benar-benar heboh, saat mereka mendengar bahwa kapal kami akan sandar dalam waktu yang cukup lama. Rambut-rambut hitam disisir sedemikian rupa, mengilap bak disiram minyak goreng. Entah parfum merek apa yang mereka pakai, baunya menyengat membuat kepala pening, menggelitik isi perutku, mual tak tertahan.
“Jakarta! Tunjukkan kembang-kembang cantikmu. Lihatlah kaptenku, tua tak ubahnya artefak berlumut, sendiri dipeluk sepi,” teriak Bono, manusia kurang ajar yang suka sekali mengejekku. Aku hanya menyunggingkan senyum seperti biasa.
Bono, ya anak lelaki itu. Aku menemukannya duduk di tepian Sungai Musi, memancing tanpa umpan. Kala itu dia masih seumuran denganku, tapi saat kutanya, dia sudah berstatus duda.
Saat kutanya lagi apakah dia bekerja? Dia menjawab, “ya, aku bekerja. Pekerjaanku memancing keberuntungan di sini.” Aku mengangguk sambil mencoba menahan tawa.
Terjawab sudah mengapa ia memancing tanpa umpan. Namun, aku terkesiap saat tali pancingnya bergerak. Ajaib! Mulut seekor ikan Nila berukuran besar menancap sempurna di kail Bono. Aku menganga melihatnya.
“Tak usah terkejut, Boi,” ucapnya.
“Bagaimana bisa?” aku masih keheranan dibuatnya.
“Tuhan tak akan membiarkanku mati kelaparan. Mungkin kesabaran dan kegigihanku mampu menarik perhatian-Nya.” Lalu Bono beranjak pergi.
“Apa aku juga salah satu bentuk keberuntungan yang diberikan padamu oleh Tuhan?” tanyaku.
“Maksudmu?”
“Bukankah hari demi hari tangkapanmu semakin sedikit?” tanyaku saat melihat tas rajut Bono yang hanya berisi seekor ikan Nila.
“Lalu, apa hubungannya denganmu? Kau mau menjual ikanmu padaku? Tak tahukah kau bahwa aku tak punya uang sepeser pun?”
“Aku punya pekerjaan bagus untukmu. Aku akan membawamu berlayar jauh meninggalkan Musi. Bagaimana? Kau tertarik?”
Bono yang berdiri tak terlalu jauh dariku hanya menatap sinis dan membalikkan badan. Lalu ia melangkah gontai meninggalkanku. Sialan, tawaranku ditolak mentah-mentah oleh seorang pemancing setengah gila.
“Woi! Siapa namamu? Hei! Bukankah tawaranku juga sebuah keberuntungan? Hei dengarkan aku, Pemancing! Bagaimana bisa Tuhan iba padamu yang tak tahu diri ini? Hei!” Aku terengah setelah berteriak sambil sedikit berlari untuk mengejarnya.
Lalu ia menoleh dan berkata, “dasar pemuda cerewet! Tunggu di sana. Aku akan mengemasi barangku. Rumahku tak jauh. Bagaimana bisa Tuhan mengirimkan keberuntungan berupa lelaki banyak bicara sepertimu. Cuihh.”
Kisah itu yang selalu kuingat kala aku melihat Bono. Kini, ia telah menjelma menjadi keberuntungan untukku. Menjadi anak buah sekaligus kakak, teman, bahkan orang tua. Meski tak henti-hentinya ia mengejekku karena aku belum menikah.
Beberapa menit lagi, kapalku akan sandar di Teluk Jakarta. Kali ini akan sandar cukup lama. Aku sengaja mengambil jatah cuti untuk menenangkan diri. Di kota ini, aku akan melepas penat. Penat karena diimpit berbagai macam masalah. Terutama masalah pasangan hidup yang tak kunjung kutemukan. Bosan rasanya saat Ibu meneleponku. Bukannya bertanya bagaimana keadaanku di tengah lautan, malah bertanya kapan kiranya aku membawa wanita untuk kujadikan pasangan.
Pertanyaannya memang sederhana, tapi jika didengarkan terus-menerus bisa membuatku gila.
Saat jangkar sudah mengait kuat, aku melangkah santai sambil memandang sekitar. Anak buahku sudah jauh di depan.
Pastilah buaya-buaya itu segera mencari mangsa. Tak akan terbersit sedikit pun bayangan anak dan istri yang sabar menunggu di pelataran jika mereka sudah bertemu wanita-wanita cantik yang menghibur kala birahi sedang kehausan.
Kadang kunasihati mereka, tapi percuma. Setan sudah bersemayam di hati dan pikiran mereka. Mengambil kendali dan kembali menjerumuskan mereka pada dunia gemerlap.
Aku yang sudah muak, memilih pergi ke Kota Tua. Duduk sendirian menikmati gedung-gedung bernuansa klasik yang artistik. Melihat Kota Jakarta yang seperti tak pernah tidur, gemerlap lampu menghias kota sepanjang malam.
Hingga tempat mungil di ujung jalan mencoba merebut pandangku, cantik nan centil dengan lampu kecil berwarna-warni. Langkah kakiku yang mulai nakal, bergerak liar tanpa bermusyawarah dengan akal.
Membawaku berdiri tepat di depan pintu kaca yang sengaja dibuat buram. Degup jantung mulai tak beraturan saat dara berbaju hitam menyambut ramah. Menawariku beberapa paket pijat refleksi. Wajah imut dengan bibir merah muda itu berbisik, “saya yang akan melayanimu.”
Sihir-sihir duniawi memang tak butuh waktu lama untuk merasuki jiwa-jiwa sepi sepertiku. Sejenak saja, sayap-sayap seakan tumbuh liar dari punggungku. Membawaku terbang dengan sensasi yang berbeda. Tak ada perlawanan sedikitpun, hanya aroma kebebasan yang kurasakan. Sejak malam itu, aku mabuk akan pesonanya. Pesona seorang bidadari yang berani menjamah kesucian jiwaku. Hubungan tanpa ikatan, tetapi selalu membuatku ingin membawanya pulang.
Memasangkan cincin di jari manisnya dan berharap hanya akulah yang boleh ia layani.
Di suatu malam, bulan terbelah menyisakan sedikit sinar untuk angkasa yang kelam. Tak seperti biasa, bidadariku menunggu di luar. Semakin dekat, semakin tampak matanya yang sembab memerah. Belum sempat bibirku bertanya, seakan ia sudah tau apa yang akan kutanyakan, lantas ia bilang, “saya hamil, Bang.”
Gemetar seluruh badanku mendengar tuturannya. Pening seketika aku dibuatnya. Belum lagi tangisannya yang pecah dalam dekapku. Ia dipecat. Aku? Aku tak tahu bagaimana caranya menyampaikan hal ini pada emak dan bapak. Aku bahagia, karena akulah yang sekarang paling berhak atas bidadari ini. Namun, aku sedih saat membayangkan emak dan bapak yang pasti sangat kecewa ketika tau bahwa aku telah membuat wanita ini hamil sebelum kata “sah” terucap.
***
Duhai Nona yang pipinya merona, bukankah tatapanmu begitu memabukkan? Lihat bagaimana kau mencairkan bongkahan es dalam hatiku. Melalui setiap kehangatan di malam-malam dingin yang sepi.
Sekarang, kubiarkan semesta merasa cemburu kala tatapanmu enggan lepas dariku. Rona kemerahan sang Surya menjadi saksi betapa aku mencintaimu. Mencintai perempuan yang menimang buah hati kami.
Memandang dunia melalui jendela rumah susun yang kami sewa. Tadi pagi, aku mengucap janji suci, kunikahi bidadariku, mengikatnya dengan kata “sah” di depan Emak dan Bapak. Meski Emak sempat pingsan dan Bapak jantungan saat menerima kabar ini.
Namun, demi kebahagiaanku mereka rela bertolak ke Jakarta. Mengantar diriku mengarungi samudera yang kupilih dengan bahtera rumah tangga yang baru saja kurakit.
Namun, ombak tak selamanya tenang. Badai tiba-tiba datang menerjang bahtera yang baru saja kurakit. Saat itu, aku berada di Tanjung Perak ketika Bono membawa kabar tak sedap.
Ia melihat bidadariku tengah menggandeng lelaki lain dan masuk dalam losmen di sekitar Kota Tua tempat Bono bekerja. Ya, Bono sudah tak jadi anak buahku semenjak kapalnya bersandar di pelabuhan yang tepat.
Ia beristrikan seorang guru ngaji dan memutuskan untuk bekerja di sebuah losmen. Mendengar kabar itu, aku bergegas pulang dengan memaksakan diri menaiki kapal kecil. Tak ada yang membuat hatiku hancur selain memikirkan nasib malaikat kecilku.
***
Aku kembali melewati jalan ini. Jalanan Kota Tua yang sempat melingkupiku dengan kehangatan. Sekarang, jalan ini menyaksikan bagaimana hatiku terbakar. Musnah tak bersisa.
Serigala betina masih bersemayam dalam diri bidadari yang kupuja. Ia liar dan tak bisa dijinakkan. Aku bak pawang sekaligus pemujanya, bahkan jika nyawaku yang ia mau, aku akan memberikannya dengan sukarela.
Dinda Agustin A.P, seorang mahasiswi semester 5 di PBSI FKIP Universitas Jember
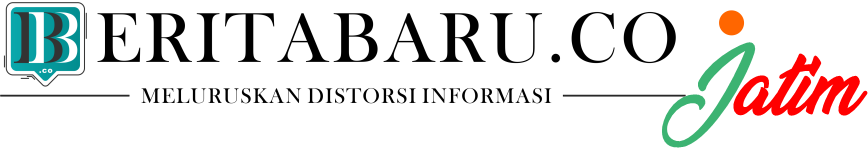
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co







