
Mahasiswa dan Kesadaran Kritis yang Harus Terus Menyala
Persoalan pendidikan merupakan penyakit akut yang menggerogoti jantung bangsa kita. Berbagai cara dan usaha sudah dilakukan untuk mencari obat mujarab dan penawarnya. Hingga kini pendidikan sebagai pilar penyangga bangsa justru digerogoti oleh birahi kapitalistik. Konstitusi hanyalah sekedar kalimat “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Kenyataannya tak sedikit regulasi yang menjadi legitimasi bagi Negara untuk menjadikan pendidikan sebagai komoditi dan Negara seolah-olah lepas tanggungjawab atas cita-cita luhur “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Dalam beberapa catatan menyebutkan, biang keladinya adalah perjanjian General Agreement on Trade and Service (GATS) yang menjadikan pendidikan sebagai sector yang harus diliberalisasi dengan 12 sektor jasa lainnya. Setan-setan global seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan World Trade Organization (WTO) adalah dalang dari semua kerusakan ini.
Di tengah pandemi yang melumpuhkan hampir seluruh sektor kehidupan, tak terkecuali pendidikan tinggi, gerakan mahasiswa merebak di beberapa tempat. Cahaya perlawanan pada penindasan sistemik dalam dunia pendidikan memancar di banyak tempat. Semua berangkat dari persoalan yang sama. Semua berangkat dari mantra yang sama. Bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara. Persoalan biaya kuliah masih menjadi problem serius yang membuat pendidikan tak bisa diakses semua golongan.
Akan tetapi justru tindakan tak akademis dan non demokratis menjadi jawaban yang dipertontonkan oleh orang-orang dilingkungan kampus. Ya lingkungan—yang katanya—akademik. Lingkungan orang-orang terdidik. Lingkungan dimana kita selaku bagian di dalamnya (mahasiswa) diajarkan apa itu hak asasi manusia, diajarkan kebebasan berpendapat, dan terus diajarkan tentang nilai-nilai demokrasi, eh tapi apa iya kampus mengajarkan itu? Upss.
Alih-alih membentuk karakter lulusan yang kritis dan memihak pada—misal—Pak Manre’ seorang nelayan Pulau Kodingareng Makassar yang menolak tambang pasir laut dan dipenjara di Polda Sulawesi Selatan atau menemani perjuangan Bu Paini yang gunung Tumpang Pitunya dikeruk kerakusan PT BSI. Kampus kini hanya menjadi tangan panjang kapital dalam menyediakan tenaga kerja murah yang mendorong mahasiswa untuk berpikir bahwa kuliah hanyalah sekedar syarat untuk menjadi “sapi perah” pemodal.
Maka tak heran ketika mahasiswa mendapatkan pendidikan alternatif di luar kampus yang membangkitkan gairah kritis mahasiswa, kampus kewalahan dan merasa terancam. Tindakan represif yang tak beradab masih menjadi senjata ampuh untuk menangkal mimpi buruk para birokrat. Penyakit yang merusak demokrasi itu kembali menjamur belakangan ini.
Lokataru Foundation dalam kajiannya menyebutkan, di era Nadiem Makarim ada sekitar 80 mahasiswa dari 6 perguruan tinggi yang didepak dari kampusnya hanya karena menyuarakan pendapat. Padahal, pendapat anak muda penting, menjadi kritis dan terlibat dalam pergerakan sosial ada pada Tri Darma Perguruan Tinggi. Catatan Lokataru Foundation belum menyantumkan beberapa kekejaman apparat negara terhadap mahasiswa. Seperti yang terakhir dialami mahasiswa-mahasiswa Universitas Negeri Solo (UNS). Poster yang mereka bentangkan ketika menyambut Presiden Joko Widodo berakhir ditangkap aparat negara.
Setidaknya, pandemi ini menjadi momentum yang tepat untuk mengetahui akar dari permasalahan yang ada.
Pertanyaan mendasar perlu kita jawab bersama, apakah pendidikan masih menjadi hak seluruh warga? Apakah selama ini biaya kuliah sudah ramah atau justru mencekik leher para mahasiswa? Bahwa kita mesti melacak dengan seksama apa yang sebenarnya terjadi, adalah hal yang sangat penting untuk menjawab pertanyaan tersebut, bila tidak kita akan jatuh pada kubangan yang sama, bahwa pendidikan hanyalah untuk mereka yang punya uang dan berani berhutang.
Kenapa Mahasiswa Tak Kritis Lagi?
Kesadaran kritis mahasiswa lagi-lagi diuji. Setelah Reformasidikorupsi September tahun lalu yang tuntutan-tuntutannya mungkin sudah banyak dilupakan. Atau perlawanan terhadap Undang-undang represif Cipta Kerja, kini mahasiswa dipaksa untuk merespon hal-hal yang selama ini dekat. Persoalan kampus sejatinya masih relevan untuk menjadi pintu masuk dalam membangkitkan nalar kritis mahasiswa yang merasakan langsung dampak penindasan. Lebih-lebih kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemic tidak ada satupun yang memihak pada pendidikan warganya, selain School From Home yang bias urban dan membongkar problem kesenjangan digital.
Tapi, seperti yang kita sadari bersama, problem serius yang menggerogoti lingkungan kampus, bukan sekedar biaya kuliah yang tinggi, namun kehidupan kampus saat ini laiknya sebuah pertunjukan teater, semua mahasiswa hanya membayar dan menikmati apapun yang dosen ucapkan. Proses belajar tersebut, seperti yang di sebut Paulo Freire sebagai Banking Education yang secara bersamaan menjadikan peserta didik kehilangan nalar kritis. Dan nalar kritis itulah sebagai senjata awal seorang mahasiswa yang kini mulai tumpul.
Hal itu sejalan dengan memudarnya tradisi membaca, berdiskusi, dan menulis di lingkungan kampus. Pengayaan pengetahuan hanya terbatas di ruang kelas yang tak lagi ramai dengan dialektika antara dosen-mahasiswa. Perdebatan substansial tak lagi terlihat karena kampus telah kehilangan aura magisnya sebagai lingkungan akademis. Dan mirisnya mahasiswa telah kehilngan cita-cita utopisnya.
Selain itu bagi Freire tujuan pendidikan adalah conscientizacao, konsientisasi, penyadaran. Konsientisasi berasal dari bahasa Brazil conscientizacao, suatu proses di mana manusia berpartisipasi secara kritis dalam aksi perubahan. Namun, iklim tersebut menjadi sekedar sekedar seolah-olah di tengah tandusnya gerakan di kampus.
Gerakan yang dimaksud tak melulu dengan turun ke jalan, melainkan gerakan ide, gerakan moral, gerakan sikap hidup, maupun gerakan sikap politik.
Organisasi-organisasi di kampuspun kehilangan tajinya. Dulu, tak sedikit mahasiswa yang nalar kritisnya dirangsang ketika aktif di organisasi kampusnya. Tapi kini, baik organisasi internal maupun eksternal—meski tak semua— mahasiswa yang aktif di organisasi memiliki sense politik yang kuat. Orientasinya berbelok dari organisasi intelektual dan gerakan menjadi sekedar organisasi yang berorientasi pada politik praktis. Maka tak heran, nada pesimisme pada organisasi kampus cukup kental. Kehidupan kampus berkembang pesat dengan segala pernak-perniknya juga menjadi salah satu aspek mengapa kesadaran kritis mahasiswa semakin pudar.
Selain meninabobokan kesadaran kritis mahasiswa, pernak-pernik tersebut juga menjadi neraka baru bagi orang tua-orang tua mahasiswa. Perkembangan fasilitas secara otomatis akan menjadi legitimasi bagi kampus untuk menaikkan biaya kuliah. Ada mantra yang selalu terdengar mengerikan, bahwa kita perlu pembangunan dan itu merupakan prasyarat kemajuan demi selembar stempel predikat dalam atau luar negeri.
Ya setiap pembangunan dan kemajuan yang dilandasi oleh hasrat segelintir pihak selalu butuh tumbal. Sikap predatoris itu kini mulai menggerogoti pendidikan tinggi, seolah-olah tertulis “Orang Miskin Dilarang Kuliah” di setiap poster-poster ‘dagangan’ perguruan tinggi. Itulah harga mahal yang harus dibayar ketika Negara angkat tangan dari tanggung jawabnya.
Ayo Nyalakan Kembali Sikap Kritismu!
Beruntungnya mimbar-mimbar bebas, lingkaran-lingkaran diskusi kritis yang sarat ilmu pengetahuan, egaliter, dan demokratis rasanya masih kental di beberapa kampus. Ghirah semangat mahasiswa tampak dari jargon yang selalu mengudara kala gerakan-gerakan mahasiswa merespon pelbagai masalah yang dialami bangsa ini, mereka masih tegas bahwa pendidikan harus tetap teguh berpegang terhadap kredo utamanya, humanism.
Antonio Gramsci mengatakan “semua orang adalah intelektual, namun tidak semua orang punya fungsi intelektual dalam masyarakat”. Intelektual organik memiliki pemahaman dan analisa yang komprehensif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Sehingga pengetahuannya mampu melahirkan kesadaran kritis untuk melakukan pemberontakan dan pembangkangan terhadap hegemoni kaum kapitalis. Sebuah keharusan bagi mahasiswa untuk turun dari menara gading dan mulai melepaskan almamater serta segala stempel di pundaknya untuk melebur dan mengakar bersama masyarakat, karena penindasan yang dialami mahasiswa juga sama seperti yang dialami masyarakat. Bila tidak kita hanya akan menjadi apa yang disebut Pramoedya Ananta Toer dalam makalahnya, sebagai intelektual blanko. Mahasiswa sebagai intelektual harus memfokuskan keberpihakannya pada masyarakat tertindas.
Bukan tidak mungkin, bila mahasiswa terus-terusan membenamkan diri mereka ke ilusi mistis tentang menjadi seorang ‘mahasiswa’, dan dengan sungguh-sungguh meniadakan semangat kritis, masyarakat akan mengutuk segala ruang-ruang ceramah dan kelas-kelas sebagai sesuatu yang berisik. Dan mengganggap mahasiswa sebagai lelucon yang paling buruk.
Kini kita seperti kembali ke masa silam. Rezim otoriter Orde Baru mulai kita rasakan saat ini. Orde baru bukan sekedar sebuah struktur pemeritahan tapi juga sebuah nalar berfikir. Kita sebagai mahasiswa harusnya mulai keluar dari belenggu-belenggu kedamaian yang mencemaskan. Merasionalkan kepengecutan sama halnya dengan melacurkan intelektualitas yang menghamba pada ketakutan. Pendidikan saat ini, kita seperti dipanggang tanpa pilihan. Dipaksa menerima api yang membakar nurani, otak, dan dompet orang tua.
Pendidikan tak lagi dimaknai sebagai hak rakyat yang harus dipenuhi oleh Negara. Selama ini Negara bukan menutup mata melainkan memalingkan muka pada sejarah dan persoalan yang ada. Hal itu sederhananya—tak bermaksud simplifikasi—bisa kita lihat dari kebijakan dalam merespon kondisi abnormal pandemi yang terjadi. Celakanya, kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan keadaan ekonomi di saat pandemi. Bahkan bila ditarik lebih jauh, kebijakan liberalisasi pendidikan justru tidak sejalan dengan konstitusi UUD 1945. Bung Hatta telah mengingatkan kita “Camkanlah, Negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila pemerintah dan masyarakat belum sanggup menaati UUD 1945, terutama belum dapat melaksanakan pasal 27 ayat 2, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34,”
Jika polemik biaya kuliah tinggi tidak segera ditangani secara serius oleh pihak-pihak terkait, atau mereka berpikir gerakan mahasiswa saat ini hanyalah drama yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka yang akan terjadi gelombang protes mahasiswa terhadap kejadian ini semakin meninggi. Esensi dari persoalan ini cukup jelas dan tampak sekali. Pendidikan adalah tanggungjawab negara dan semua warganya bisa mengakses dengan mudah. Memang ada rasa sakit dalam memperjuangkan kebebasan dan keadilan. Sekaligus kita semua harus percaya, tanpa memberikan apapun pada prinsip-prinsip keadilan, tidak akan menghasilkan apapun di bidang kebebasan. Wallahu a’lam.
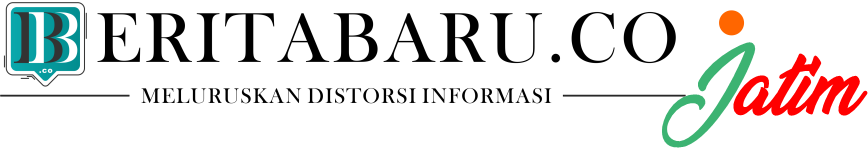
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co






