
Infodemi

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Kejadiannya 2016, istilah post-truth dinobatkan menjadi word of the year versi Oxford Dictionary; dengan memanggul prestasi, “terkait dengan atau menandai sebuah keadaan yang di dalamnya fakta obyektif kurang berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi”.
Lihatlah bagaimana makhluk bernama post-truth ini dijabarkan. Meskipun, istilah ini cukup telat masuk ke negeri kita sebab, mungkin benar kata Pak Pejabat, birokrasi kita ruwet untuk urusan beginian. Ia baru booming pertengahan 2018-2019. Post-truth setidaknya menandakan dua hal: pertama, agaknya kita harus mulai menerima bahwa kita, manusia, ternyata tidaklah se-rasional yang kita bayangkan. Selalu ada bias yang entah disadari atau tidak. Kedua, kita juga harus menerima bahwa saat ini kita hidup dalam keadaan di mana kebenaran fiksional dapat diyakini sebagai kebenaran bukan karena jalan pembuktian, namun pengulangan secara masif dan serampangan. Membuahkan ‘fakta alternatif’ menurut istilah Kakanda Trump.
Tentu, Sidang Pembaca boleh menyederhanakannya: loh, ini, kan, hanya urusan informasi dan bagaimana orang mencernanya. Memang, tapi sayangnya keadaan ini membuncah menjadi keruwetan baru sebab agaknya, naluri cerewet manusia menemukan ladang terbaiknya pada perkembangan teknologi informasi dan media massa. Lalu lintas informasi, kalau penulis boleh umpamakan, ibarat ratusan atau ribuan bahkan jutaan burung beo menyanyi terus-terusan dengan suara serak, dan sialnya, suara-suara itu berebut masuk ke kuping kita yang kebetulan hanya ada dua. Kemudian di tengah dengung menyesakkan itu, kita duduk pada satu kursi, sendirian menjaga kewarasan agar tetap sehat dan berbahagia.
Penulis sadar, luberan informasi ini adalah sebuah keniscayaan. Zaman, pada akhirnya, pasti diubah dan berubah, sesuai dengan kaidah ‘manusia menciptakan sesuatu dan sesuatu itu kelak akan mengubahnya’. Begitulah. Manusia menciptakan internet, sebuah medium baru, dan kelak ia akan mengubah cara berpikir dan hidup penggunanya. Akhirnya media bukan hanya penyebar informasi, tapi media adalah pesan itu sendiri. Dekade 60-an, Marshall McLuhan telah menyebut demikian; tertuang dalam bukunya yang telah menjadi legendaris (sebab ia menulis pada era ketika internet masih ngendon dalam kepala penemunya), Understanding Media. Dengan celetuknya yang terkenal: medium is a ma(e)ssage.
Maka belakangan ketika virus Covid-19 menyebar dan tiba-tiba kita panik dan ribut soal pukul berapa sebenarnya berjemur yang benar itu, ini bisa menjadi alarm bahwa, mungkin luberan informasi telah mencapai fase berbahayanya. Sebab ia justru tak membuat penerimanya ‘sehat’, melainkan cemas dan bingung dan tak ketemu pegangan. Ia telah menyebabkan disorientasi, mungkin juga paranoid.
Haidar Bagir, seorang esais yang konsen dengan isu budaya dan agama, pernah menyebut zaman kita dengan istilah zaman kacau. Nicholas Carr dengan enteng menyebut generasi internet (maksudnya kita) adalah ‘orang-orang dangkal’ tanpa kedalaman—Siwalan betul kamu Carr! Dalam The End of Expertise (2017) Tom Nichols lebih serius lagi, ia mengeluh orang-orang Amerika (sebagai sampel penelitiannya) tengah terobsesi dengan kedunguannya sendiri; akibat antusiasme berlebih terhadap informasi khususnya di dunia maya. Mungkin memang informasi simpang siur telah menjadi makanan pokok bagi kita hingga mematikan saraf dan kita tak tahu kapan harus berhenti.
Namun bukan berarti luberan informasi hanya mengandung keburukan-keburukan. Penulis juga sadar, keterbukaan informasi di satu sisi adalah esensi demokrasi. Ia akan menegakkan banyak teropong baru dan memungkinkan kita mengawasi kekuasaan bahkan dari sudut pandang tidak penting sekalipun. Ia bisa menjadi belatung yang akan menggerogoti totalitarian dan hegemoni penguasa. Pada sudut ini kita bisa bersyukur, namun dalam konteks menjaga kecukupan informasi agar tetap waras di tengah pandemi covid-19 ini, penulis akan menyarankan beberapa hal berikut.
Pertama, jadikanlah informasi sebagai suplemen saja. Kita tak bisa menganggap bahwa memang membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya, apa pun itu, agar dapat bertahan. Suplemen, apabila berlebih justru dapat menjadi racun. Informasi pun demikian, secukupnya akan lebih baik. Kedua, setidaknya kita dapat memulai kebiasaan menelesuri asal-usul informasi dan (sekali lagi) menyadari bahwa kita tidaklah se-rasional yang kita duga. Selalu ada bias, semacam celah masuknya kepentingan berupa keyakinan pribadi dalam menerima dan menafsirkan informasi. Kita tak perlu grusa-grusu, kesasa-kesusu. Kita, kan, nggak ingin selamat dari Covid-19 dengan pikiran agak bermasalah sebab stres terlalu banyak mengonsumsi informasi yang tak jelas lagi tak perlu.
Apabila mau, kita juga boleh memilah dan meragukan setiap informasi dengan ciri tertentu sebab, menurut Geger Riyanto dalam Asal-usul Kebudayaan (2018), ‘sesuatu akan menjadi kebenaran apabila kita meyakininya terlebih dahulu’. Berilah sedikit ruang untuk ‘keyakinan’ itu agar tak bersifat absolut. Sedikit ruang yang, bakal ditempati gairah meragulan dan menelesuri apabila sempat dan perlu.
Terakhir, entah mengapa penulis tiba-tiba teringat kritik jenaka Julius Henry “Groucho” Marx, orang lucu dari Hollywood sana, hampir setengah abad silam untuk setiap pembodohan di televisi, bunyinya: i find television very educating. Every time somebody turn on the set. I go into the other room and read a book. Nah, sekarang di tangan sidang pembaca-lah pilihannya, apakah hendak menambahkan ‘internet’ setelah televisi dalam kritik itu dan pergi membaca, tak cuma buku dan segala yang bersifat teks, namun alam dan diri sidang pembaca sendiri juga enak untuk dibaca. Sekali lagi, lakukanlah ini apabila sempat, ingin, dan perlu saja. Tak ada yang memaksa. Begitu. (*)
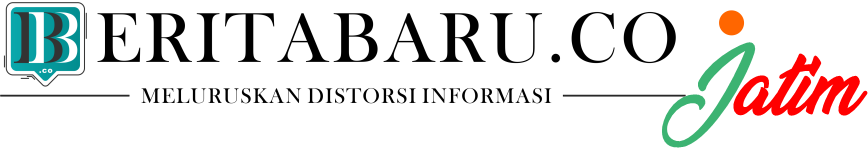
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co






