
Saat Berita Bahagia Itu Datang Menjelang Malam
Sandal jepit yang semakin tipis terus dipaksa menopang beban manusia berwajah tirus itu. Pipinya semakin kopong. Wajahnya pusat pasi. Dinding-dinding kusam di setapak lorong yang ia lewati itu seolah menyapa dalam hening. Remang neon kuning yang menggantung jarang-jarang itu pun semakin memperkeruh kesepian yang melandanya.
Tak ada lalu-lalang manusia. Ia seorang diri berjalan dan terus menyeretkan kakinya. Sesekali kerikil-kerikil kecil ia tendangi. Lorong di pinggiran kota itu menjadi penanda ia akan tiba di suatu tempat di mana tubuhnya merebahkan badan di sepetak kamar seluas selonjoran kaki dengan kasur tipis yang tak lagi berbusa dan lemari kardus di sampingnya.
Lorong pesakitan itu saban hari ia lewati. Sendiri. Ia hanya dikawani sandal jepit berwarna hijau dan selembar handuk putih yang warnanya telah kecoklat-coklatan. Sebelum matahari terbit, dengan perut lapar sisa semalam ia selalu menyusuri rumah-rumah semi permanen khas urban. Celana selutut menggantung di tubuh kerontangnya.
Pelan-pelan kompleks perkampungan perantau itu ia lewati. Perjalanannya menuju tempat menggantungkan hidup dan mengundi nasib di kota yang jahat padanya tepat di sebrang jalan bawah fly over. Matahari mulai mengintip derap langkah kakinya. Perutnya semakin keras meronta untuk disumpal meski dengan pisang goreng. “Sebentar lagi kita makan,” ujarnya pada bunyi-bunyi kelaparan.
Berangkat dari desa di pelosok timur jawa bukan kemauannya. Sepetak lahan yang ia rawat dengan bahagia memaksanya berjudi di kota. Bapaknya yang sakit keras menuntut ia menggadaikan lahan pada tuan tanah di desa. 3 tahun sudah ia bertahan di carut-marut perkotaan namun uang tebusan beserta bunganya masih juga belum terkumpul. Bagaimana tidak, seseorang yang mengajaknya bekerja justru tak lagi kelihatan batang hidungnya tepat seminggu sebelum gajinya dibayar.
Laki-laki itu bekerja di sebuah gedung berlantai 27 sebagai kuli bangunan. Berangkat dengan 7 temannya ia rela meninggalkan dua adiknya yang masih berseragam putih merah. Dan si bungsu masih belajar berlari. Semua ia tinggalkan demi mimpi menebus lahan satu-satunya yang ia miliki.
Hanya saja, mimpi buruk itu datang tiba-tiba. Ke tujuh temannya seketika langsung pulang seminggu setelahnya. Sedang ia sudah memantapkan hati keluar dari desa dan pulang bawa segopok uang.
Terkatung-katung tanpa uang hanya mampu ia lakoni tiga hari. Di hari keempat ia tak lagi sanggup selalu mengisi keroncongan perutnya dengan menenggak air kran PDAM kamar mandi. Di saat menghilangkan suntuk berjalan di trotoar jalan, ia memergoki laki-laki seusianya, berdiri dengan kemucing di tangan. Tanda tanya memenuhi kepala.
“Dia kerja?” “Kerja ke siapa?” “Berapa gajinya?” “Gimana cara daftarnya?” Dan pertanyaan-pertanyaan polos lain khas pencari kerja. Tak perlu pikir ini-itu, ia mantapkan langkahnya untuk langsung memberondong lelaki berkemucing itu dengan tanda tanya di kepalanya.
“Tak ada bos di sini. Hanya saja kau perlu “izin” ke pria itu,” ujar pria berkemucing sembari menudingkan telunjuknya ke laki-laki di warung pojok.
“Siapa dia?” Ia bertanya dalam hati. Tak berani ia tanyakan langsung.
“Abang itu yang pegang wilayah sini,” lanjut pria sembari membersihkan beton untuk duduk. “Sini. Santai dulu.”
Ia semakin bingung, laki-laki jangkung bertubuh kurus berkaos hitam polos itu adalah preman di sekitaran fly over. Pengamen, pedangan kacang, hingga pria yang sedang duduk di sampingnya tunduk padanya. “Saya pengen ikut kerja di sini, Bang,” ia membuka obrolan saat dua cangkir kopi hitam datang.
“Kau bilang langsung ke Abang saja ya. Dia nanti yang atur kerjaan untuk kau.”
Rasa penasarannya pada Abang makin tinggi. Ia percaya apa yang pernah diucapkan sang bapak, bahwa manusia bukanlah apa yang ia lihat. Tak sedikit hal-hal yang tak bisa kita lihat selain dengan rasa. Perkara mata gampang menipu, tertipu.
“Bang, aku pengen ikut cari makan di sini.” Dengan sedikit ndredeg ia membuka pembicaraan di sela-sela hisapan kreteknya. Kepulan asap meluncur beserta mata tajam yang menatap dari ujung kaki hingga kepala. Tetiba ia tersenyum. “Kau baru di daerah sini?”
Lelaki yang dalam kepalanya terpatri sebagai sosok menakutkan, tak bisa tersenyum, seketika runtuh. “Belum sebulan, Bang. Kemarin di kerja di gedung sebrang. Mandornya lari,” ia berusaha mengisahkan mimpi buruk yang menimpanya.
“Kau merokok?” Ia menyodorkan sebungkus Gudang Garam. “Hidup di kota yang buas pada siapapun butuh mentalitas petarung. Mereka yang bekerja di sini bukan pecundang,” ia menghisap kembali kretek tangan itu.
“Tidak ada bos disini. Kita semua sama. Hanya beda tugas. Tugasku kebetulan bagian menghajar dan menghabisi orang-orang yang berani ngerecoki daerah sini. Dan tugasmu temani aku ngopi tiap pagi di sini.”
Ia kaget. Pekerjaannya hanya menemani ngobrol seorang bertubuh kurus dengan rambut sebahu. Rasa penasarannya pada sosok pria mengagetkan makin membuncah. “Kenapa kau bisa sampai ke sini?” Pertanyaannya memecah lamunan penasaran.
“Ingin menebus sepetak lahan yang terpaksa digadai untuk menebus obat bapak di apotik, Bang,” katanya sambil pelan-pelan menuangkan kopi hitam. “Makin lama makin membengkak ternyata. Susah banget berurusan dengan orang-orang kaya mati nurani.”
Ketawa derita lepas dari tenggorokan pria yang hampir lupa tertawa. “Hanya berusaha.”
“Kapan kau akan pulang?” Abang yang akrab disapa Tole itu seketika merubah raut wajah ramahnya.
“Aku ikut.”
Seketika lekaki pesakitan dan menyedihkan itu buntu. “Apalagi yang Tuhan kirim padaku setelah merasa diselamatkan dari nyanyian lapar tengah malam.” Ia menggugat Tuhan. Pesakitan dan kehidupan menyedihkan yang selama ini menguntit di setiap langkahnya tiba-tiba dihentikan sepasang mata ramah Abang Tole.
“Bahkan untuk sekedar berharap pun aku hampir tak memiliki daya. Tuhan menggerakkan tangan-Nya melalui nurani pria di pojok warung bawah fly over.” Ia menggerutu bahagia dalam hati.
“Aku masih simpan sedikit tabungan kawan-kawan di sini. Bisa kau pakai dulu.” Darah marah Abang Tole tampak dari telunjuk bernada mengancam yang ia mainkan.
Lelaki menyedihkan itu kini kembali memberanikan diri merapal mantra-mantra harapan.
Di bawah kasur ruangan kusam itu, Abang Tole menyimpan sepucuk beceng. “Terakhir kali selongsong peluru berhasil menembus dada kiri pria penagih hutang,” ucapnya sembari meniup peredam ujung bedil warisan kakeknya.
“Kini, aku akan habiskan satu ledakan peluru di hati setan desa yang terus mengancam kawanku. Kawan baru ku.”
Penindas berwajah malaikat macam tuan tanah pantas mati tersungkur. Perkara dosa biar aku urus dengan Tuhan. Kerna Tuhan tak mampu mengurus masalah kawanku. Kawan baruku. Biar mesiu ini yang menyelesaikan.
“Seorang pria ditemukan tewas di lahan perkebunan tebu dengan dada kiri tertembus peluru. Diduga ia dibunuh”
Begitulah dua koran lokal menuliskannya. Koran itu kini dipegang oleh tangan yang jempolnya menarik pelatuk pistol. Abang Tole tersenyum sinis. Lelaki yang duduk di depannya tidak lagi semenyedihkan sebelumnya.
Aura kebahagiaan itu terpancar dalam wajah lelaki itu. Pelan-pelan ia pun ikut tersenyum. “Aku keingat aja saat menjelang magrib, pelatuk beceng itu kau tarik, Bang,”
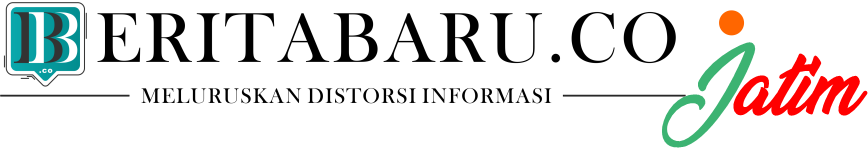
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co






