
Tragedi Kekerasan di Perguruan Tinggi Agama: “Catatan Hitam” Program Moderasi Kemenag
oleh: Mashur Imam*
Tragedi Kekerasan terhadap beberapa demonstran di Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember merupakan coreng hitam yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi upaya pengembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia. Lembaga yang berada di bawah naungan kementerian agama (Kemenag) ini, seharusnya menjadi potret budaya Islam yang rahmatal lil ‘alamin. Semestinya, dapat menjadi kluster pengembangan praktek nilai-nilai moderat Islam sebagai akar pendidikan yang terbuka dan berkedamaian.
Miris, jika lembaga yang diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memerangi kekerasan atas nama komunal agama, malah menjadi ruang terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ini tentu merupakan masalah yang lebih urgen bagi Kemenag, dari pada hanya menyoroti persoalan desibel suara toa adzan masjid.
Memasuki tahun 2022, telah ada dua kejadian kekerasan yang viral di lingkungan perguruan tinggi Islam negeri, yakni di UIN Alauddin Makassar dan UIN KHAS Jember. Kronologi keduanya tentu berbeda. Walaupun demikian, keduanya memiliki pola konflik yang hampir senada.
Dalih aksi kekerasan yang digunakan sama tentang perlawanan atas kelompok pengkritik yang dituduh subversif karena mengganggu ketertiban. Korbannya, tentu juga sama, yakni para mahasiswa dari masing-masing perguruan tinggi ini. Dari berita yang beredar, utamanya di UIN KHAS Jember, belasan korban yang luka-luka dan ada yang sampai dilarikan ke pusat layanan kesehatan setempat.
Bahkan, sejumlah pihak telah melaporkan kasus ini ke kepolisian. Sayangnya, walaupun sudah masuk sebagai kasus pelanggaran berat, Kemenag belum merespon kasus ini. Padahal kasus demikian merupakan kesempatan untuk memperbaiki image agama yang selama ini menjadi sumber pertikaian politik.
Sekitar bulan September tahun lalu, Kemenag merilis buku pedoman penguatan moderasi agama di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang paling nyata, pada tahun kemarin juga, direktur jenderal pendidikan Islam mengeluarkan surat keputusan dengan nomor 879 tentang petunjuk tehnis rumah moderasi agama. Kebijakan ini guna memperkuat perguruan tinggi agama sebagai pusat atau sumber ajaran yang penuh rasa cinta dan kasih.
Dua aturan ini menunjukkan, Kemenag ingin menghadirkan agama sebagai ruh kedamaian, keharmonisan dan kemajuan bangsa Indonesia. Tentunya, seluruh pihak perlu mengapresiasinya. Namun apa guna kebijakan pemerintah jika hanya sebagai sumber penghasilan para birokrat.
Jika tidak ada efek positifnya, tentu kita boleh menyebutnya sebagai kebijakan pemborosan anggaran. Kebijakan dikeluarkan hanya agar jadi “program atau proyek baru” yang berguna sebagai sumber ceperan tambahan bagi ASN yang menjadi pelaksananya. Dengan kata lain, kebijakan moderasi agama hanya sebagai dasar legalitas pengambilan kas negara oleh aparaturnya.
Jika memang serius dalam hal menggaungkan ajaran agama sebagai “inspirasi” dalam mencapai “kedamaian” dan “kemakmuran” masyarakat, seharusnya yang disorot adalah sesuatu yang menjadi masalah dari kedua hal penting ini. Betul memang, solusinya adalah moderasi agama. Namun, tidak bisa hanya sebagai wacana saja, atau hanya jadi ilmu yang praksisnya masih lemah dan cenderung melangit.
Nilai moderasi agama semestinya dapat membumi, menyentuh persoalan kedamaian dan kemakmuran manusia secara praksis. Moderasi agama harus lahir sebagai paradigma atau bahkan metode dasar (manhaj) tindakan sosial masyarakat. Ia mestinya dilahirkan secara sosiologis menjadi anti tesa persoalan yang merusak kehidupan manusia. Jika yang merusak adalah pertentangan kelas agama, aliran, kapital dan struktur politik, maka nilai moderasi harusnya menjawab soal-soal itu.
Nilai moderasi agama mesti merukunkan kelas kiri-kanan, borjuis-proletar, pemerintah-rakyat, mayoritas-minoritas dan seluruh pertentangan kelas lainnya yang berpotensi menimbulkan kerusakan (mafasid). Jika tidak demikian, wacana moderasi hanya merupakan brand program yang ujung-ujungnya malah memperkeruh kelas yang ada. Yang awalnya dua kelas (kiri-kanan, borjuis-proletar dan sebagainya), berubah menjadi tiga kelas yakni ketambahan kelas moderasi sebagai komunal yang berbeda dan saling bermusuhan juga dengan kelas lainnya. Artinya, dalih moderasi malah memperluas konflik dan tentu pelanggaran kemanusiaan terus dapat terjadi.
Nilai moderasi yang selama ini diwacanakan oleh Kemenag, mestinya diterapkan lebih dahulu di kelembagaan pendidikan, utamanya perguruan tinggi, yang ada di bawah naungannya. Hal ini berkenaan dengan fungsi kampus sebagai sumber agen dan kontrol budaya dan bahkan kehidupan sosial-politik masyarakat.
Kita tentu telah belajar sejarah besar bangsa ini, bahwa seluruh perubahan baik gerak reformasi maupun kontestasi gagasan falsafah bangsa selalu bersumber dari gairah budaya pendidikannya. Dari gagasan Soekarno, Syahrir, Nurcholis, Gus Dur, Mahfud hingga Fadli Zon sekalipun, banyak dipengaruhi oleh pengalaman belajar saat di kampusnya masing-masing.
Dengan kata lain, aset utama dalam mengembangkan ide terbaik demi kemajuan bangsa ini adalah berkembangnya budaya pendidikan tingginya. Dalam konteks masalah yang terjadi tentu sama. Kebijakan moderasi agama akan sukses menjadi program perdamaian dan kemakmuran negara ini, apabila dapat diproduksi secara baik di lembaga pendidikan tinggi.
Hal yang perlu perhatikan dewasa ini, seberapa jauh peran perguruan tinggi Islam dalam menjadi lokomotif moderasi agama masyarakat? Sejauhmana mereka dapat membentuk masyarakat yang damai dan makmur? Bagaimana peran mereka dalam menyelesaikan konflik seluruh kelas yang ada? Tentu hal ini belum terbaca secara signifikan.
Yang pasti, belum ada satupun perguruan tinggi yang mengambil peran penyelesain konflik borjuis-proletar hingga konflik pemerintah-rakyat. Malah ada kabar buruk, konflik kekerasan dan diskriminasi kelas juga terjadi di tempat yang mestinya menjadi awal penyelesaian diskriminasi.
Salah satu contohnya, kekerasan yang terjadi di UIN KHAS Jember. Perguruan tinggi ini sejak awal (sebelum kebijakan moderasi agama lahir) getol mendedikasikan sebagai “pusat kajian Islam Nusantara” dan bahkan telah menjalankan program rumah moderasi agama. Dari gairah yang diwacanakan, sudah bakal tentu perguruan tinggi ini menjadi sumber penanaman nilai moderasi sebagai jalan kedamaian dan kemakmuran masyarakat.
Namun, berdasar fakta kekerasan baru-baru ini yang terjadi, cukup menjadi indikator ketidaksuksesan bahkan bisa dianggap perusak target kebijakan moderasi agama yang didengungkan selama ini.
Berdasar dalih ketertiban, mahasiswa dituduh subversif dan dipukuli. Kelas elit struktural kampus atas nama efesiensi dan keamanan menghajar mahasiswanya sendiri. Yang demikian tentu tidak akan terjadi, jika moderasi sebagai nilai dan manhaj telah tercipta secara baik dalam iklim budaya perguruan tingginya.
Nilai moderasi yang mengarah pada semangat toleransi keterbukaan (tasammmuh), dan keadilan (ta’addul) mestinya sudah tumbuh menjadi bunga yang dapat berbuah sebagai alat perdamaian dan kemakmuran masyarakat. Jika yang demikian tidak bisa dimulai dari perguruan tinggi agama Islam, tentu akan ada difabelitas upaya penguatan budaya moderasi agama yang selama ini menjadi program unggulan Kemenag.
Mustahil juga, mengharapkan perguruan tinggi manjadi garda terdepan dalam membumikan ajaran Islam sebagai gairah kemakmuran masyarakat. Untuk menyelesaikan masalah sendiri saja tidak mampu, mustahil out putnya mampu menyelesaikan masalah diskriminasi dan konflik kelas dengan segala variannya.
Untuk itu, sudah saatnya Kemenag menfokuskan pada masalah pokok yang manjadi target wacana moderasi agama. Persoalan suara toa masjid, manasik haji hingga dana abadi pesantren, memang penting diurus.
Namun, untuk urusan agama sebagai jalan perdamaian dan solusi menghadapi diskriminasi sosial, satu-satunya kunci yang dapat diupayakan adalah terciptanya budaya moderasi. Yang tentunya dapat dimulai dari penguatan ruang sumber nilainya, yakni budaya pendidikan tinggi agama Islam.
Jadi uruslah lebih dahulu, kekerasan yang mencoreng nilai baik agama! Biar tak disangka hanya ngurusi pendapatan tambahan atas dasar agama.
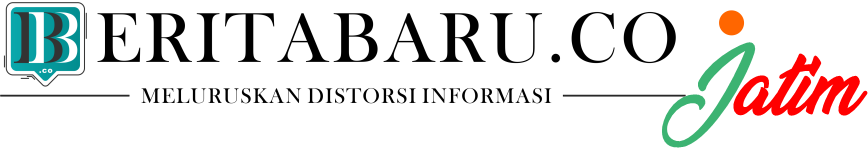
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co







