
Tuhan Tidak Pernah Melempar Dadu
Kisah ini aku tulis hanya untuk pengingat bahwa aku pernah ada dan menjejakkan kakiku di kota yang nyaman ini, Yogyakarta dan menjejakkan rasa di hatinya, lelaki penebar pesona.
Hans, seperti yang aku katakan, ia adalah lelaki yang tidak tiba-tiba datang dan mengulurkan tangan juga senyumnya padaku. Ia datang atas kehendak Tuhan, kehendak yang aku hanya bisa merabanya, mungkin saja Tuhan mengirimnya untuk mengusir sepiku, mungkin saja Tuhan menempatkannya untuk menjadi penjagaku, mungkin juga Tuhan mendatangkannya untuk mengantarkanku pada hal-hal baru, atau bisa jadi Tuhan membawanya padaku untuk menguji imanku, atau bahkan Tuhan mengirimnya sebagai malapetaka baru dalam hidupku. Tapi persetan dengan semua kemungkinan-kemungkinan itu, bukankah aku hanya tinggal menjalani dan menikmatinya? Toh tidak ada yang sia-sia di dunia ini.
Ia adalah lelaki yang dengan firman-firman filsafatnya mendongengiku perihal kebenaran juga perihal keraguan yang disertai dalil dari Rene Descartes De Omnimbus Dubitandum, bahwa segala sesuatu harus diragukan. Meragukan kebenaran adalah hal yang harus dilakukan manusia, agar ia tidak terjebak dalam kungkungan pemikiran yang dangkal. Yang lebih antusias lagi, ia mendongengiku perihal buku-buku, dan laut, dan gunung, dan budaya, dan seni yang ia geluti selama ini. Ia pintar sekali membidikkan panahnya, ia tahu apa yang menjadi kegemaranku. Aku mendengarnya dengan sesekali tak acuh sembari memainkan gadgetku. Dasar pejantan, ia selalu punya banyak cara untuk menjerat betinanya, umpatku dalam hati.
Teringat perkataanmu, Hans, lelaki dengan sifat binatangnya hanya mempunyai satu tujuan, tak lebih dan tak kurang adalah nafsu birahi. Dari perkataanmu itu, aku mulai menyangsikan, apakah memang ada cinta di dunia ini, jika kemudian birahi adalah tujuan akhirnya. Atau mungkin benar apa yang engkau katakan, nafsu adalah puncak dari cinta itu sendiri. Nafsu adalah hakikat dari cinta itu sendiri.
Namun bukankah manusia, dalam hal ini lelaki, seringkali merusak puncak cinta itu? Memburu nikmatnya selangkangan perempuan dengan mengatasnamakan cinta, keinginan, kebutuhan, atau dengan dalil-dalil lainnya yang keluar dari mulut manisnya yang sejatinya adalah racun yang melumpuhkan dan merusak daya pikir, menjadikan birahi untuk menjerat erat setiap perempuan yang ia inginkan, menjadikannya tergantung padanya hingga sang perempuan kehilangan daya nalarnya dan merangkak di bawah ketiaknya. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, para lelaki itu bebas memuncratkan cairan kentalnya di setiap kelamin perempuan lain yang ia kehendaki. Sangat binatang bukan? Hingga aku pada satu kesimpulan bahwa setiap lelaki di dunia ini adalah binatang, mereka hanya menunggu waktu, kapan sifat kebinatangannya itu ia hadirkan.
Padanya, lelaki penebar pesona, aku hanya ingin melihat sejauh mana ia bisa mempertahankan idealisme dan kecerdasannya ketika berhadapan dengan seorang perempuan yang bernama, Galuh Candra Kirana. Aku yang akan merangkak di hadapannya ataukah dia yang akan bersujud di hadapanku. Kau bilang jangan bermain api, namun bukankah dia yang memulainya, bukan aku, Hans? Aku hanya memberi reaksi dari aksi yang ia berikan.
Sebagai lelaki, ia mempunyai bungkus yang menarik dan nyaris sempurna, ia tampan, tinggi, kulitnya yang bersih membungkus dagingnya yang utuh, dan ia memiliki kecerdasan yang bisa menarik setiap perempuan untuk mendekatinya. Namun entah apa yang ada dipikirannya, ia malah tertarik padaku atau bisa jadi karena pesonaku yang tidak bisa ia elakkan, entahlah, biarkan saja itu menjadi haknya dan aku tidak ingin mencampurinya.
Dan di sore ini, Hans, setelah perjuangannya yang begitu keras untuk mendekatiku, aku meloloskan permintaannya untuk mengajakku jalan melihat pesona pantai Parangtritis kala malam menjemput, pantai yang memang sudah sejak lama ingin aku datangi, –pantai yang sejatinya ingin aku jamah keindahannya denganmu, namun hingga detik lelaki penebar pesona itu mengajakku, kau belum juga meloloskan permintaanku- hingga aku penuhi permintaannya, selain itu, juga karena aku ingin membunuh sepiku, sendiri berada di kamar berukuran 3 m x 3 m hampir membuatku gila. Membuat dadaku semakin sesak dengan segala kenyerian yang selama ini menyergapku.
Kami pun menyusuri jalanan yang berdebu, sesekali ia mendongeng tentang film kesukaannya, Ia bercerita sambil sesekali tertawa lepas, aku bisa merasakan kegembiraannya yang membuncah, Hans, sesekali aku turut tersenyum sembari menikmati harum parfumnya yang menguar bersama angin yang masuk di lubang hidungku.
Matahari sudah tenggelam di sudut barat saat kita sampai di pantai Parangtritis. Setelah memarkir motornya, kami pun berjalan menyusuri bibir pantai sambil sesekali membiarkan ombak mencium telapak kaki kami, kami biarkan sepatu kami basah. Ia lelaki humoris, Hans, ia tahu bagaimana membuat perempuan nyaman dan tertawa lepas saat berada di sampingnya. Sesekali ia sengaja mencuri pandang pada wajah di sebalik kerudungku, aku tahu itu dari sudut mataku. Setelah lelah berjalan, kami duduk di atas pasir sambil memandang laut lepas, seperti yang pernah kita lakukan dulu, Hans, ketika aku dan kamu duduk di atas pasir pantai yang tak jauh dari pantai Parangtritis, entah apa nama pantai itu, aku lupa -kalau kamu ingat beritahu aku nama pantai itu- kami bicara tentang banyak hal, ia bercerita tentang keluarganya, tentang alasannya sampai di kota ini, hingga ia mulai bicara tentang kesepiannya, tentang hatinya yang pernah terluka dan juga tentang sajak Hamlet yang diserukan pada Ophelia:
Ragukan bahwa bintang-bintang itu api;
Ragukan bahwa matahari itu bergerak;
Ragukan bahwa kebenaran itu dusta;
Tapi jangan ragukan cintaku.
Diakhir sajak itu ia berhenti, kemudian berkata lirih:
“Kamu tentu pernah jatuh cinta.”
Aku mengangguk.
“Dan kamu tentu juga tahu bagaimana rasanya jatuh cinta.”
Lagi-lagi aku hanya mengangguk. Aku tercekat, tiba-tiba ia menatap lekat mataku, kamu tahu, Hans, lewat tatapan matanya, ia berusaha masuk ke pedalaman mataku dan mencoba menelanjangi hatiku.
Tatapan matanya menjadi begitu teduh, ada ketakutan menjalar di aliran darahku. Ketakutan yang bercampur dengan riak-riak kecil di hatiku. Ya, Hans, hatiku bergejolak, sebergejolak saat engkau pertama kali tatap mataku ketika engkau pertama kali hadir untuk mendongengiku perihal hakikat cinta yang kau agungkan itu. Segera aku lempar pandanganku pada langit yang mulai gelap. Ombak bergulung dan pecah di antara hitamnya pasir pantai ini, aku raup dan aku lemparkan pasir itu sekuat mungkin ke arah di mana ombak berkecamuk. Aku ingin pembicaraan ini disudahi karena aku tahu kemana pembicaraan ini akan berujung.
“Sepertinya angin pantai ini sudah mulai membuatku menggigil. Sebaiknya kita segera pulang.” Aku berkata padanya dan membangkitkan tubuhku.
Ia turut berdiri dan memegang kedua pundakku, ia hadapkan tubuhku padanya, ia paksa aku memandang kedua matanya yang berkilatan.
“Menggigilmu bukan karena angin pantai ini, menggigilmu karena ketakutanmu terhadap apa yang akan aku bicarakan.”
Nafasku serasa berhenti, ia dapat membaca pikiranku. Ia agresif sekali, Hans, tidak memberiku ruang untuk mengelak, ia terus menyerangku. Perkenalan kami yang masih begitu singkat sudah membuatnya seberani ini padaku.
Aku berjalan meninggalkannya yang berdiri mematung di belakangku.
“Kalau kamu tidak ingin pulang, aku bisa pulang sendiri.”
Teriakku padanya. Segera ia mengejarku dan menjejeri langkahku. Ia pun menarikku untuk menaiki motornya. Sepanjang perjalanan, kami sibuk dengan pikiran masing-masing. Ia menjadi pendiam, dongengan-dongengannya tak lagi keluar dari mulutnya yang tipis. Sepertinya ia sedang menikmati kekalutan hatinya.
Benar katamu, Hans, sekali aku menerima tawarannya, harapannya akan membumbung, sekali aku menerima tawarannya, sama saja aku memberinya lampu hijau untuk teus mendekatiku. Aku takut terjebak, Hans.
Setelah perjalanan dengan suasana yang begitu kaku, sampailah kami di mulut gang tempat aku tinggal. Aku memintanya menurunkanku di situ. Semula ia menolak, tapi aku bilang padanya, jika ia tidak menuruti keinginanku, jangan pernah lagi bicara padaku. Kami berdebat agak lama, hingga akhirnya ia menurutiku, sebelum ia hilang dari pandanganku, ia sempat bisikkan sesuatu di telingaku, Hans, ia katakan: “Tuhan tidak melempar dadu, tapi aku yang akan mendapatkannya dengan caraku sendiri.”
Aku termangu, mencoba menerka maksud dari ucapannya, sepertinya benar apa yang aku bilang padamu semalam bahwa semakin aku menghindarinya, semakin dia akan mengejarku, semakin aku menolaknya, semakin kuat keinginannya untuk mendapatkanku.
Aku juga membenarkan apa yang kamu utarakan semalam bahwa jangan mendekati api, karena sekarang, aku sudah terkena jilatannya, ini berarti aku harus berjuang memadamkannya atau ia akan membakar dan melalap habis tubuhku.
Sekian, Hans, ini yang dapat aku tulis untukmu malam ini, semoga kamu bisa memahaminya, selamat menikmati malammu. Semoga engkau bahagia di manapun berada.
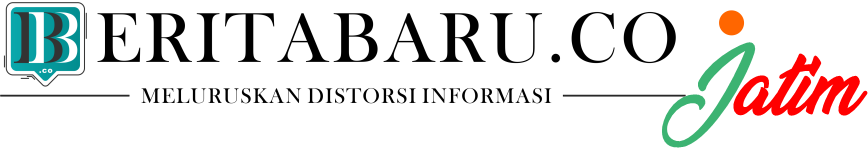
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co







Kereeeen kakak…