Pengarang Kami Telah Berhenti Menulis
Pengarang Kami Telah Berhenti Menulis
Oleh: Ibnu Wicaksono
(Manager Gamelan Cilik SDN Kemuningsari Lor 02 Kecamatan Panti, Jember)
Cerpen — SUNGGUH, kabar itu telah menggetarkan semua dada kami. Betapa tidak, pengarang kami yang telah menerbitkan belasan novel, puluhan cerpen, dan beberapa puisi itu telah berhenti menulis. Maka dari itu, kami selaku tokoh-tokoh dalam karangan sastranya, merasa perlu untuk membahas persoalan genting ini. Sungguh, ini kabar yang amat menggetarkan.
Di negeri alinea yang teduh, tepat di bawah rimbun pohon frasa, kami melingkar, membicarakan nasib kami yang tak tentu arah, sebab pengarang kami telah membuat keputusan yang tak disangka-sangka.
Kami adalah para tokoh yang lahir dari kisah-kisah pengarang kami. Sudah ratusan tokoh yang ia lahirkan, lebih tepatnya sih diciptakan, ya. Tapi, pengarang kami bukan tuhan, hanya penulis biasa, yang tak rajin-rajin amat menulis. Ia juga sering malas bangun pagi, kadang minum kopi sampai dini hari, bahkan bisa dikatakan jarang sekali mandi. Cuma semangatnya akan bergairah tinggi kalau ia sedang menciptakan tokoh-tokoh seperti kami.
Untuk itu, kami perlu berkumpul mengumpulkan gagasan, musyawarah dengan serius, menyatukan suara untuk kemudian mempertanyakan: mengapa pengarang kami memutuskan untuk berhenti menulis.
Tak sedikit, tokoh-tokoh diantara kami marah karena kisahnya tak selesai, tokoh-tokoh diantara kami juga kecewa karena sudah menderita dalam kisahnya atau tokoh-tokoh diantara kami juga ada yang diciptakan tanpa perenungan yang dalam, hanya muncul begitu saja tanpa pendalaman watak yang sempurna.
“Anjing! Gimana nih nasib saya. Enak aja dia bikin tokoh kayak saya, eh ternyata sekarang, dia malah nggak nulis!” Kata Jenar, salah satu tokoh dari Cerpen ‘Perempuan Yang Memotong Lidah Tetangganya’
“Setan! Gue juga udah diperkosa, nih. Berkali-kali sama ratusan lelaki yang dia ciptakan. Memang setan, dia!” Marah Laksmi, satu-satunya tokoh perempuan dari Cerpen ‘Di Mata Laksmi Ada Surga’.
“Astagfirullah. Tenang. Jangan pakai emosi.” Sahut Ainun, tokoh dari Novel ‘Megatruh’.
“Kita demo saja dia.”
“Ya, benar. Ayo kita demo. Kita harus mendesak agar dia menulis kembali.”
“Semua harap tenang, tenang. Jangan grusa-grusu, mari diminum dulu kopinya.” Tokoh Bening dari Cerpen ‘Tingkepan di Tangkuban Perahu’ berusaha menenangkan keadaan, ia yang sejak tadi subuh di dapur, memang sengaja membuatkan kopi karena persoalan gawat ini tak bisa dihadapi dengan emosi yang penuh bara. Harus tenang.
Maseda, selaku tokoh yang dianggap paling tua memimpin musyawarah. Maseda adalah tokoh pertama yang dibuat oleh pengarang kami dan kisahnya belum selesai-selesai sampai hari ini. Tapi dialah yang paling bijak di antara kami dan paling bersabar menanti agar kisahnya diselesaikan oleh pengarang kami.
“Kawan-kawan memang perlu bersabar dan tenang menghadapi persoalan ini. Pengarang kita memang berhenti menulis. Cuma seharusnya, saya yang menjadi korban paling sedih, karena sejak ia menulis, saya menjadi saksi atas penciptaan kalian. Dan sampai hari ini, kisah saya juga belum selesai-selesai.” Kata Maseda berusaha meredam suasana dan mengajak kami untuk lebih tenang.
“Terus gimana dong?”
“Iya, gimana dong?”
“Aku punya ide.” Usul Niluh, tokoh dari Cerpen ‘Perempuan dan Senyum Senja’.
Sontak, semua tokoh memusatkan perhatian ke wajah Niluh. Maseda memberikan ekspresi wajah tanda mempersilakannya untuk berbicara.
“Gimana kalau kita mengutus Jilan, tokoh dari Cerpen ‘Wawancara dengan Pembunuh Munir’ untuk datang mewawancarai pengarang kita? Bukankah itu bisa menjawab semua pertanyaan kita.” Usul Niluh.
“Tapi ‘kan itu berbahaya, kalau pertanyaan Jilan menyinggung perasaan pengarang kita, bagaimana?” Tanya Ainun.
“Ya tenang saja to. Jilan kan wartawan. Pasti cerdas dia bikin pertanyaan yang tidak menyinggung perasaan.”
“Iya, setuju.”
“Ya, Ya. Setuju.”
Kami pun menyetujui usulan Niluh. Maseda menugaskan Jilan untuk mewancarai pengarang kami. Di gapura negeri kami, kami berbaris melepas Jilan yang segera melaksanakan tugas mulia bagi tokoh-tokoh seperti kami. Dengan memakai baju putih lengan panjang berdasi, celana hitam, juga tas miring berwarna cokelat, topi mirip pelukis, dan sepatu vantofel, Jilan berangkat mengunjungi pengarang kami.
Sembari menunggu Jilan, kami mengisi hari-hari kami dengan kerja bakti, banyak selokan paragraf yang perlu dibersihkan, di ujung gang tanda baca, juga perlu dicat kembali. Kami melakukan kerja bakti di negeri alinea yang kami cintai sambil berharap-harap cemas, kira-kira apa jawaban dari pertanyaan: mengapa pengarang kami berhenti menulis.
Pertanyaan itu terus bertebaran di kepala kami, bahkan Tokoh Ibu Sumiarti, dari Cerpen ‘Guruku Tak Pernah Menangis’ mengajarkan pertanyaan itu pada tokoh murid-murid dari Novel ‘Telaga Kecil’ sambil kerja bakti. Berminggu-minggu, negeri kami bekerja bakti, karena juga ada kabar virus ‘ambiguitas frasa’ mulai menyerang. Maka dari itu, kami perlu membersihkan kotoran-kotoran paragraf di halaman kami. Walaupun sebenarnya, ada persoalan yang lebih penting dari virus ‘ambiguitas frasa’, ya persoalan tentang pengarang kami itu.
Waktu yang dinanti-nanti datang juga. Jilan berjalan dari kejauhan menuju pohon frasa, tempat biasa kami berkumpul. Kami pun bergegas melingkar dan siap mendengarkan cerita tentang alasan mengapa pengarang kami berhenti menulis.
Jilan duduk sebentar, menyeruput kopi pemberian Bening, sebentar. Lalu bersiap bercerita.
“Jadi begini kawan-kawan.” Jilan mulai bersuara. Kami pun dengan kesungguhan hati dan keseriusan tingkat tinggi menyimaknya.
“Waktu saya datang ke rumah pengarang kita. Dia terlihat duduk di ruang tamu, dan menjauh dari kamarnya, yang mana, kamarnya itu adalah tempat biasanya ia mengarang dan menulis kisah-kisah tentang kita.
Setelah dipersilakan untuk masuk dan duduk, saya berhati-hati dan bermaksud untuk mulai bertanya. Tiba-tiba, malah pengarang kita yang membuka suara.
” Jilan, sepertinya aku tidak akan menulis lagi. Aku sudah muak dengan dunia kepenulisan. Dan sebenarnya, rasa-rasanya aku tak benar-benar sedang menulis. Tulisan-tulisanku adalah tulisan sampah. Tulisan omong kosong serapah. Semua aku kerjakan hanya karena kepentingan. Ada novel yang aku tulis karena aku ingin terkenal dan dapat uang, ada cerpen yang aku tulis karena ingin masuk koran, bahkan sampai aku bikin puisi biar diterima cintaku oleh Mirna, kekasihku yang sudah aku putuskan.
Aku seperti berdosa selama ini. Aku yang seharusnya memberikan warna-warna baru untuk perkembangan dunia kesusasteraan, malah menulis dengan kepentingan sereceh itu, kepentingan murahan semacam itu.” Pengarang kita meminum kopinya, lalu melanjutkan bercerita kepada saya.
“Untuk apa aku menulis, jika ternyata tulisan-tulisanku masuk di koran, lalu koran itu dijadikan bungkus kacang kulit. Untuk apa aku menulis, jika ternyata yang aku kejar hanyalah kepopuleran dan uang. Untuk apa aku menulis. Aku merasa tidak berguna, Jilan.”
“Jadi, gara-gara itu, Tuan berhenti menulis?”
“Bukan.”
“Lalu, apa Tuan?” Saya bertanya dengan hati-hati. Pengarang kita menelan ludah sebentar, menatap jendela sebentar, lalu menatap lampu seperti mengingat sesuatu.
“Dua minggu yang lalu, aku mengalami hal-hal yang ganjil. Aku bermimpi, dan pada tiap mimpi-mimpiku itu, aku didatangi oleh tokoh-tokohku, ya termasuk kamu, Jilan.
Kalian semua menyampaikan hal yang sama. Pesan yang serupa. Kabar tentang perempuan. Bahwa ada seorang perempuan di tengah hutan, sendirian mengalami kesedihan yang mendalam. Perempuan itu menangis tak henti-henti. Dalam mimpiku, kalian menyuruhku untuk mendatangi perempuan itu. Apabila aku bisa menghentikan tangisan perempuan itu dengan tulisanku, maka aku baru bisa disebut sebagai penulis yang benar-benar penulis. Karena dalam mimpi itu, kalian seperti meneror tiap aku tidur, makanya aku gelisah dan mencemaskannya.
Aku pun mencoba pergi ke hutan, sesuai alamat yang disampaikan kalian dalam mimpiku. Dan ternyata, memang benar adanya. Ada perempuan yang tak henti-hentinya menangis. Singkat cerita, aku berikan tulisanku yang pertama padanya sambil berkenalan, tapi aku gagal. Kemudian aku berikan tulisanku yang kedua, ia malah menyobek kertas yang berisi tulisanku. Sampai aku berusaha menghentikan tangisnya dengan cara apapun, tapi aku tetap gagal, Jilan.
Dari situ, aku pulang. Berjalan memunguti kenangan tentang kesedihan yang berceceran di rebah jalanan. Dan mengutuk diri sendiri, bahwa aku tidak pantas menjadi penulis. Kau lihat mataku, sampai hari ini air mataku ini pun juga ikut-ikutan menangis.”
“Jadi, Tuan menangis ini gara-gara perempuan itu? Atau Tuan menangis ini gara-gata gagal menjadi penulis yang benar-benar penulis? Atau Tuan menangis ini gara-gara gagal membuat perempuan itu berhenti menangis?” Saya bertanya pada pengarang kita dengan penuh penasaran dan hati-hati.
“Entahlah, aku juga cemas dengan diriku. Aku juga tidak dapat menjawab, mengapa aku tidak berhenti menangis.”
Jilan berhenti bercerita. Lalu meminum kopi pemberian Bening, sebentar. Kami yang sedari tadi berkonsentrasi mendengarkan Jilan bercerita, semakin menambah kadar keseriusan.
“Jadi pengarang kita itu, sekarang tak hanya berhenti menulis. Tetapi dia juga menangis?” Tanya Maseda pada Jilan.
“Iya.”
“Dan, pengarang kita itu terus menangis, tidak berhenti-berhenti?”
“Iya.”
SUNGGUH, dada kami semakin bergetar. Persoalan tentang pengarang kami menjadi semakin serius, menjadi semakin rumit. Masalah dia berhenti menulis saja belum dapat kami selesaikan, malah muncul masalah baru. Dan, kami pun semakin serius untuk memecahkan dan mencari solusi, bagaimana agar pengarang kami itu tidak hanya kembali menulis, tapi juga berhenti menangis.
Jember, 6 Maret 2020
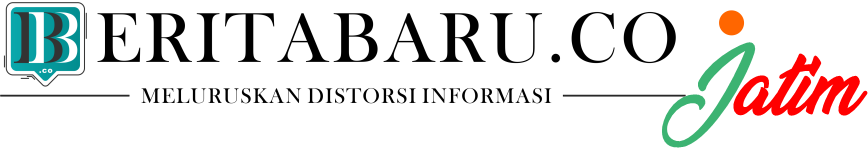
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co







