
Perempuan dan Antisipasi Kekerasan Budaya di Masa Transisi
oleh: Akhmad Taufiq*
PASCA penetapan oleh KPU pada 20 Maret 2024 terhadap hasil Pilpres, yang mencatatkan kemenangan pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terlepas masih adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi, pasangan ini belum tampak menyiapkan tim transisi. Terlepas tim transisi itu dipandang penting atau tidak, masa transisi itu tidak dapat dihindari. Terdapat beberapa agenda politik penting yang mesti disiapkan oleh presiden terpilih. Tapi, dari sekian agenda politik itu, yang tidak kalah penting dirumuskan adalah mengantisipasi ledakan persoalan sosio-ekonomi dan kultural. Mengingat masa transisi cukup panjang sampai dengan Oktober 2024, sebagai masa pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru terpilih.
Masa transisi itu, bagaimanapun dapat diposisikan sebagai suatu kondisi yang kompleks. Dari sisi perempuan, masa transisi saat ini ditandai dengan beban sosial-ekonomi, politik, dan kultural yang cukup serius. Bagi perempuan, beban sosial-ekonomi ini menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Meskipun, lebih dari itu terdapat persoalan yang lebih besar, yang dimungkinkan dapat terjadi, yakni kekerasan budaya pada perempuan di masa transisi.
Antisipasi Kekerasan Budaya
Kekerasan budaya yang selama ini didefinisikan sebagai bentuk terjadinya tindakan yang menghambat akses yang berbasis pada persoalan etnisitas, agama, dan ideologi. Pada faktanya, kekerasan budaya itu dapat terjadi dalam skala yang lebih luas (Galtung, 1996). Akses perempuan dan juga termasuk di dalamnya anak-anak, difabel, dan kelompok masyarakat miskin sebagai kelompok rentan, yang tidak mendapat perhatian yang lebih serius dari struktur berbasis negara, maka dimungkinkan proses ini dapat menimbulkan terjadinya kekerasan budaya.
Tentu, faktor hambatan dan praktik pengabaian atas akses perempuan dan kelompok rentan itu dapat semakin memperparah kondisi perempuan, jika negara di masa transisi ini tidak menyiapkan sedemikian rupa ruang kebijakan yang memadai untuk mereka. Perempuan dan kelompok rentan itu hanya menjadi ladang eksploitasi politik elektoral pada masa pilpres yang lalu. Proses mobilisasi perempuan oleh beberapa kelompok politik dengan berbagai agenda dan modus politik, sebenarnya disadari atau tidak merupakan bentuk kekerasan budaya, tepatnya kekerasan budaya politik yang menimpa mereka. Terdapat kesadaran palsu secara ideologis bagi perempuan dan kelompok rentan itu ketika dimobilisasi demi kemenangan calon tertentu.
Hal ini diperparah pasca-Pilpres, secara ekonomi mengalami problem serius, ketika aneka rupa bantuan pada masa kampanye dan saat Pilpres sudah habis dan kemudian diikuti dengan melonjaknya harga barang dan jasa. Proses berikutnya dapat menjadi persoalan yang lebih kompleks dari sekadar soal ekonomi keluarga. Hal ini terjadi karena perempuan secara kultural pada masyarakat kita memiliki kecenderungan sebagai tumpuan terakhir manajemen ekonomi keluarga.
Kecenderungan Politik yang semakin Maskulin
Persoalan demikian itu diperparah oleh satu kecenderungan, jika presiden terpilih nantinya lebih menggunakan pendekatan maskulin dalam praktik kekuasaannya. Dengan latar belakang militer dengan segala atribut politik yang melekat, maka wajah kekuasaan politik tampak lebih powerfull dan maskulin. Kecenderungan politik yang semakin maskulin ini tentu dapat menjadi ancaman bagi demokrasi, yang esensinya lebih mengedepankan pendekatan feminin, berupa terbukanya ruang dialog dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sipil tentu lebih bahagia (well-being) ketika rezim kekuasaan lebih menampakkan wajah feminin, wajah yang humble, familier, dialogis, sekaligus peduli terhadap persoalan-persoalan fundamental masyarakat sipil, yang otomatis sensitif terhadap persoalan perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Lewis (2007) menyatakan bahwa masyarakat sipil yang well-being itu akan terwujud, jika telah menjadi fokus perhatian di ruang publik, yakni ketika kebahagiaan meningkat, yang ditandai peningkatan kesejahteraan, stress yang rendah, dan ruang publik yang terbuka dan ramah. Hal ini dapat terjadi, jika rezim yang berkuasa nantinya dapat memastikan bahwa ruang demokrasi itu berkembang secara lebih baik, diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang kondusif.
Di masa transisi ini, perlu suatu usaha untuk melakukan antisipasi, agar kekhawatiran itu tidak menjelma menjadi kekerasan budaya yang semakin massif, sebagai akibat dari pengabaian atau lalainya penyelenggara negara. Pengabaian dan kelalaian penyelenggara itu adalah sebentuk kekerasan struktural yang dapat berakibat pada kekerasan budaya. Perempuan dan kelompok rentan dalam hal ini adalah pihak pertama yang merasakan segala akibat buruk dari kekerasan struktural itu. Perlu suatu usaha untuk me-recovery dan sekaligus mengoptimasi peran strategis perempuan dan kelompok rentan sebagai representasi masyarakat sipil di masa transisi ini untuk kebutuhan strategis di masa mendatang.
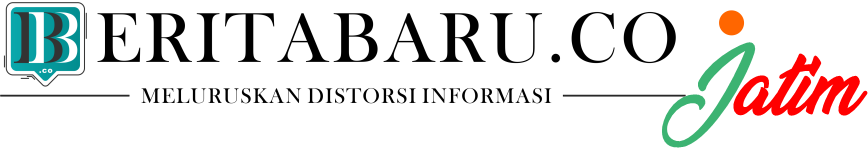
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co






