Jembatan Rialto dan Cerita Pendek tentang Bayangan
Cerpen — “Kelak, sehabis tubuh ini rapuh sendiri, bayangan kita akan menyatu kembali. Bersama senja dan air mata….”
Dan sepasang kekasih itu saling melepas. Bersama senja. Bersama angin. Tak ada yang merasa meninggalkan atau ditinggalkan. Hanya ada satu fragmen yang membuat sepasang kekasih itu mengalami kesedihan yang sama, yaitu kehilangan.
***
Waktu bergerak. Tahun terus mengulang Januari. Kota ini pun tumbuh bersama air yang katanya, suatu hari nanti akan menenggelamkan kota ini, kota Vanesia. Kota jembatan. Kota masker. Kota mengambang. Kota kanal. Begitulah orang-orang di seluruh dunia menyebutnya. Dan di sepanjang kanal yang berliku-liku, di sepanjang ratusan jembatan yang menyilang, atau di setiap bangunan-bangunan yang tumbuh di atas air, akan selalu ada manusia yang memutar ingatan dan menciptakan kenangan. Selalu seperti itu. Seperti diorama yang picisan, namun begitu ampuh untuk dileburkan ke dalam sebuah cerita yang mengandung unsur kesedihan.
Di sisi tua jembatan Rialto, pada dinding-dinding batu yang dingin, senja menciptakan bayangan tubuh manusia. Bayangan itu milik seorang lelaki yang berjalan perlahan-lahan ke arah seorang wanita berkacamata dengan rambut tersanggul.
“Aku kenal sepasang matamu!” ucap lelaki itu ketika berhadapan dengan wanita itu.
Wanita itu cukup lama berpikir. Barangkali lupa. Tapi beberapa detik kemudian, setelah ia memaksa merobek ingatannya, akhirnya ia ingat.
“Giuseppe!?”
Di jembatan tua yang tiba-tiba menjadi panggung opera itu, aura romantis seperti menguap begitu saja dari permukaan. Dan apabila senja, merpati-merpati, riak air, angin, tangga berbatu, dapat menceritakan dan menggambarkan bagaimana sepasang manusia itu mengalami situasi yang paling dramatis, maka seperti inilah jadinya:
“Sejak aku terlahir, telah kuciptakan begitu banyak bayangan. Dan bayangan, membuat manusia menjadi lebih hidup. Aku telah berkali-kali menyaksikan bagaimana sepasang kekasih saling berpelukan. Tapi kali ini aku merasa ada yang beda. Sepasang manusia itu terlihat sangat menikmati pelukannya tanpa peduli dengan suasana sekitar. Sungguh pemandangan yang indah. Lebih indah daripada tubuhku,” kata senja.
“Baru pertama kali ini aku melihat wanita itu. Sepertinya ia bukan berasal dari kota ini,” ucap salah satu merpati.
“Apakah kita bisa saling memeluk seperti mereka?” tanya merpati lain.
“Mana mungkin! Kita kan, tidak punya tangan,” tegas yang lainnya.
“Aku kesusahan melihat mereka. Tapi aku merasakan betul kehangatan bayangan mereka yang menyentuh sebagian tubuhku,” bisik riak air.
“Sebagai salah satu elemen yang tak pernah diam, aku selalu menghampiri mereka, menghantam tubuh mereka, membelai rambut mereka, menyentuh kulit, masuk ke pori-pori, urat, nadi, dan terus masuk lagi sampai aku terdampar di hati mereka. Dan yang aku rasakan hanyalah kegelisahan,” tutur angin.
“Tapi akulah yang selalu merasa terbebani, akulah yang selalu menjadi tumpuan sebelum mereka menginjakkan kaki di jembatan itu. Coba bayangkan bagaimana rasanya menjadi tangga berbatu yang selalu dilewati orang-orang sebanyak mampu?”
Dan begitulah ketika elemen-elemen di sekitar jembatan itu ikut andil dan memberikan sudut pandangnya masing-masing. Namun saat sepasang manusia itu mulai membuka mulut dan seperti ingin berbicara lagi, seolah semuanya–senja, merpati-merpati, riak air, angin, tangga berbatu–ingin menghentikan aktivitasnya dan memasang hening hanya untuk mendengarkan percakapan sepasang manusia itu. Barangkali hanya angin yang tak bisa diam.
“Sudah sangat lama, Giuseppe….”
“Ya. Sudah sangat lama… jangan kau lepaskan lagi genggamanmu ini, Mai!”
“Mana mungkin aku bisa melepaskan sesuatu yang bisa membuatku merasa tak sendiri lagi?”
Giuseppe menatap lama sepasang mata yang memasang air mata. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia bingung. Tapi kemudian ia bertanya, “Bagaimana kau bisa sampai ke sini?”
“Memang keinginanku untuk menghabiskan masa tuaku di sini. Dan kebetulan anak pertamaku tinggal di kota ini.”
“Apa kabar keluargamu?”
“Aku punya tiga anak laki-laki dan satu lagi perempuan. Cucuku sudah sembilan.”
“Bagaimana denganmu?” tanya Mai kemudian.
“Anakku dua, semua perempuan. Sedangkan cucuku semuanya laki-laki, ada tujuh.”
“Tampaknya kau tak sesubur anak-anakmu.”
Sejenak mereka berdua tertawa ringan. Dan tentu saja gigi mereka dapat dihitung dengan mudah. Mereka perhatikan suasana sekitar; menikmati hangatnya senja, mengenang kembali apa-apa yang sudah. Lalu tubuh mereka merapat ke sisi jembatan, melihat sungai yang jernih, melihat Gondola yang bergerak di bawah jembatan. Dan ketika rasa lelah menjalar ke seluruh tubuh, mereka kemudian saling membantu untuk duduk pada bangku yang telah disediakan di sana.
45 tahun yang lalu, ketika pertama kali mereka sama-sama menyatakan cintanya di jembatan Rialto itu, mereka paham bahwa berpisah adalah pilihan setelahnya. Sebab mereka mengerti filosofi keluarga mereka sendiri. Giuseppe adalah keturunan asli dari kota ini, sedangkan Mai dan keluarganya adalah pendatang dari Vietnam yang memilih untuk berdagang di kota Venesia. Tentu saja ketika mereka memaksakan hubungan, maka kedua keluarga yang berbeda latar belakang itu tidak akan pernah sependapat. Andai saja mereka hidup di zaman modern, barangkali tak akan ada perbedaan suku, tak akan ada yang mempermasalahkan dari mana asal mereka, di mana mereka dilahirkan, atau berjidad agama apa yang mereka yakini.
Kenyataannya mereka pun berpisah. Menjalani kehidupannya sendiri-sendiri. Menikah dengan pasangannya masing-masing. Beranak-cucu. Sampai masing-masing pasangan mereka meninggalkan mereka terlebih dahulu. Istri Giuseppe meninggal di usia 30 tahun karena serangan jantung. Tentu saja ia sangat merasa sedih, walaupun sebagian besar perasaannya hanya untuk Mai. Sedangkan suami Mai meninggal di usia 45 tahun. Ia tertabrak kereta ketika hendak menyelamatkan anak laki-laki yang bermain bola di dekat rel. Tapi Mai, sama sekali tidak merasa sedih atas kepergian suaminya.
Tapi entah mengapa, dalam cerita pendek, waktu terasa begitu cepat berlalu. Dan di sinilah mereka sekarang. Di kota Venesia. Dipertemukan kembali di sebuah jembatan tua yang telah memisahkan mereka hampir setengah abad. Mereka menyulam kembali kenangan, merekatkan kembali ingatan, di hadapan senja yang masih saja terdiam menyaksikan kemesraan mereka.
“Akankah kita bertemu kembali, esok atau lusa, Giuseppe?”
“Aku harap setiap senja kita akan selalu bertemu di sini, Mai.”
“Ya, kuharap begitu.”
“Kau tahu, Giuseppe,” lanjut Mai, “kita seperti sepasang anak muda yang dipermainkan oleh cinta.”
“Ha-ha.”
Percakapan mereka tampak lebih santai. Kadang mereka bercerita bagaimana awal mereka bertemu, bagaimana dulu mereka sering pergi ke gedung opera untuk melihat pertunjukan teater, atau saat festival topeng yang selalu digelar di St. Mak’s Squere setiap tahunnya. Kadang mereka tertawa ketika mengingat kembali detik-detik perpisahan mereka. Mereka tertawa bahwa sebenarnya, perpisahan adalah kunci untuk kembali bertemu. Dan kepergian adalah labirin yang selalu bertumpu pada satu titik, yaitu kepulangan.
Maka pada setiap senja, mereka akan selalu berada di jembatan tua itu. Hanya demi menikmati sisa umur mereka. Hanya demi sebuah kebahagiaan yang tertunda di masa lalu. Dan setiap kali mereka berpisah untuk pulang kepada keluarganya masing-masing, mereka merasa pada saat itulah pertemuan mereka yang terakhir. Sehingga meraka akan selalu menyadari betapa waktu sangatlah berharga.
***
“Ayah, ayah… kenapa sekarang Nenek sering keluar pas sore hari? Sekarang Nenek juga sering dandan. Sering senyum-senyum sendiri juga. Aneh kan?” tanya cucu Mai yang paling kecil saat melihat neneknya yang melangkah ke luar rumah dengan membawa seikat bunga.
Namun sang ayah hanya diam. Dan gadis kecil itu memasang wajah cemberut, “Huh, kenapa Nenek selalu melarang Raina untuk ikut?”
Entah kenapa ayah gadis kecil itu hanya bisa terdiam. Tatapannya begitu kosong, seperti sedang merasakan kesedihan yang begitu mendalam.
Sementara di jembatan Rialto, Giuseppe sudah menunggu, duduk bahagia sambil menghisap sebatang cerutu. Tak lama kemudian ia lihat Mai mulai mendekat. Ia juga lihat senja yang kemerah-merahan itu berjatuhan dan memantul-mantul di kacamata milik kekasihnya. Lantas keduanya berpelukan. Mesra sekali. Giuseppe sedikit menunduk untuk mencium tangan keriput kekasihnya. Namun tiba-tiba ia tertahan. Ada sesuatu yang mengganjal pikirannya.
“Sejak kapan kita tak memiliki bayangan?”
Mai hanya tersenyum. Barangkali Giuseppe lupa, atau bisa saja ia hanya pura-pura lupa untuk menghibur kekasihnya. Tetapi senja dan angin tak akan pernah lupa dengan apa yang pernah Giuseppe katakan 40 tahun lalu, “Kelak, sehabis tubuh ini rapuh sendiri, bayangan kita akan menyatu kembali. Bersama senja dan air mata….”
Kemudian malam datang bersama rembulan. Senja hilang, merpati-merpati pulang, riak air menjadi dingin, angin semakin tak bisa diam, tangga berbatu sejenak menghela napas, dan sepasang kakek-nenek itu masih di sana, berpelukan tanpa bayangan. (*)
*Cerita ini terinspirasi dari puisi Goenawan Mohamad yang berjudul, “Marco Polo”
ALIF FEBRIYANTORO, lahir di Situbondo, 23 Februari 1996. Berdomisili sementara di Jember. Buku kumpulan cerpennya yang akan terbit, Sebelum dan Setelah Hujan, Sebelum dan Setelah Perpisahan (2020).
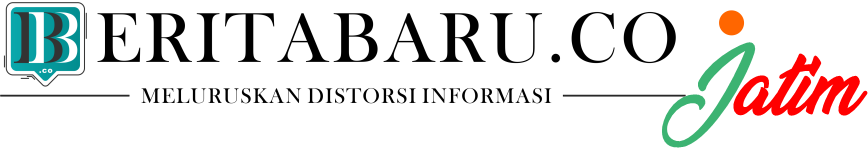
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co







