
Kritik 100 Hari Kerja Bupati: Dana Rp 22 Miliar Habis untuk Proyek Fisik, Pembangunan Kehilangan Kompas Moral
oleh: Abdur Razak – Ketua PC PMII Probolinggo
PEMERINTAH Kabupaten Probolinggo baru-baru ini menggulirkan program 100 hari kerja yang diklaim sebagai bentuk percepatan pelayanan dan pembangunan. Dengan anggaran sebesar Rp22 miliar, program ini diluncurkan dalam kemasan “perubahan cepat” dan janji besar akan transformasi. Namun, di balik semangat yang dikobarkan, publik dihadapkan pada pertanyaan penting dan mendasar: apakah program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat? Atau justru menjauh dari substansi dan sekadar menjadi panggung pencitraan yang mahal?
100 Hari: Gebrakan Cepat atau Kosmetik Demokrasi?
Dalam tradisi politik lokal, program 100 hari kerap dijadikan simbol awal untuk menunjukkan arah dan komitmen seorang pemimpin baru. Ia bisa menjadi ajang untuk membuktikan keseriusan dalam membenahi persoalan, sekaligus sinyal terhadap gaya kepemimpinan yang akan dijalankan. Namun, ketika program ini tidak dibarengi transparansi, evaluasi objektif, serta partisipasi masyarakat, maka besar kemungkinan program tersebut tidak lebih dari sekadar kosmetik demokrasi.
Program 100 hari kerja Kabupaten Probolinggo tampak didominasi oleh proyek-proyek fisik yang cepat dilihat hasilnya, seperti pengecatan trotoar, pemugaran kantor, penataan alun-alun, dan seremoni bersifat simbolik lainnya. Ini menjadi masalah ketika pembangunan fisik tersebut tidak dibarengi dengan upaya menyelesaikan persoalan dasar yang lebih mendesak dan struktural seperti kemiskinan, gizi buruk, dan pendidikan.
IPM Tak Capai Target, Bukti Kegagalan Prioritas
Untuk menilai keberhasilan arah pembangunan, indikator yang paling otentik dan tak bisa dimanipulasi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencerminkan sejauh mana negara atau daerah berhasil memenuhi tiga kebutuhan dasar warganya: pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Namun, data IPM Kabupaten Probolinggo tahun 2024 justru menunjukkan kegagalan dalam mencapai target. Pemerintah menetapkan target IPM sebesar 71,26, namun realisasinya hanya 70,85. Penurunan performa ini patut dikritisi, apalagi jika dibandingkan dengan tren sebelumnya di mana realisasi IPM tahun 2022 dan 2023 justru mampu melampaui target. Ini berarti bahwa pada tahun ketika anggaran digelontorkan secara besar-besaran untuk program percepatan, hasilnya justru di bawah ekspektasi.
Pencapaian ini seharusnya menjadi alarm keras bagi para pengambil kebijakan. Apa artinya pembangunan cepat jika gagal meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Apa gunanya renovasi trotoar, pengecatan taman, atau pemugaran alun-alun jika gizi buruk masih menghantui anak-anak, dan fasilitas kesehatan dasar belum menjangkau wilayah pinggiran?
Kemiskinan Tak Terkendali, Tapi Uang Habis untuk Mempercantik Alun-alun
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah angka kemiskinan. Tahun 2023, realisasi kemiskinan justru meningkat menjadi 17,19%, melebihi target yang dipatok sebesar 16,21%. Tahun 2024, meskipun sedikit membaik di angka 16,45%, capaian ini tetap berada di atas target ideal yaitu 16,00%. Artinya, program-program penanggulangan kemiskinan belum menyentuh akar persoalan dan belum mampu menciptakan dampak signifikan.
Sementara itu, dana Rp22 miliar justru dikucurkan untuk program-program 100 hari yang didominasi kegiatan fisik, yang dalam banyak kasus tidak berkontribusi langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan. Renovasi alun-alun, pengecatan bangunan, atau penataan taman kota memang bisa memberi kesan indah dan rapi, namun tidak menjawab kebutuhan warga yang masih kesulitan mengakses gizi, pendidikan, lapangan kerja, dan layanan kesehatan.
Apakah layak menggunakan anggaran sebesar itu ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi? Bukankah seharusnya alokasi dana difokuskan untuk membangun infrastruktur kesehatan di wilayah-wilayah tertinggal, memperluas akses pendidikan, atau menyediakan pelatihan dan jaminan sosial bagi buruh tani serta masyarakat pinggiran?
Pembangunan yang Tidak Manusiawi
Salah satu proyek yang paling menonjol dalam program 100 hari adalah renovasi alun-alun. Meski secara visual memberi kesan “pembenahan,” namun secara esensial proyek ini justru menjadi simbol pembangunan yang tidak manusiawi. Di saat IPM gagal tercapai dan angka kemiskinan belum menurun signifikan, penguasa justru memilih mempercantik wajah kota ketimbang memperkuat isi rumah tangga rakyat.
Apakah keindahan ruang publik lebih penting dibanding asupan gizi anak-anak yang mengalami stunting? Apakah rumput sintetis lebih mendesak daripada akses air bersih dan sanitasi layak di wilayah pelosok? Apakah pencahayaan malam hari di taman kota lebih urgen dibanding keberadaan guru dan fasilitas sekolah yang layak? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan betapa arah pembangunan kita kehilangan kompas moral. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang memanusiakan manusia, bukan sekadar membangun kota agar terlihat “maju” di depan kamera.
Minim Transparansi, Rawan Politisasi Anggaran
Yang juga mencemaskan adalah minimnya transparansi penggunaan anggaran. Hingga hari ini, belum ada dokumen resmi yang dirilis secara terbuka kepada masyarakat mengenai rincian kegiatan, alokasi dana, indikator capaian, serta evaluasi dampaknya. Tanpa transparansi, pengawasan publik melemah. Dan ketika pengawasan publik lemah, maka pengelolaan anggaran sangat rawan ditunggangi oleh kepentingan politik jangka pendek dan kepentingan elite lokal.
Jika program 100 hari ini hanya menjadi arena konsolidasi loyalis birokrasi dan proyek-proyek yang dikerjakan oleh kontraktor tertentu, maka makna pelayanan publik akan sirna. Yang tersisa hanyalah politik anggaran, yang menjadikan rakyat sebagai penonton dari anggaran yang tidak mereka rasakan.
Bupati Harus Memimpin dengan Substansi, Bukan Popularitas
Sebagai kepala daerah, bupati punya mandat besar untuk memimpin dengan visi yang kuat dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat kecil. Bukan menjadi pemimpin yang sibuk memburu popularitas dalam waktu singkat. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan gebrakan yang mencolok mata, melainkan kebijakan yang menjangkau hidup mereka secara langsung dan berkelanjutan.
Pembangunan yang sejati bukan soal siapa yang paling cepat mengubah wajah kota, tapi siapa yang mampu memperbaiki kualitas hidup warga, terutama mereka yang paling terpinggirkan. Kepemimpinan yang berpihak pada rakyat adalah kepemimpinan yang berani menunda proyek pencitraan demi memperkuat fondasi kesejahteraan.
Saatnya Kembali ke Akar
Program 100 hari boleh saja menjadi momentum awal untuk menunjukkan arah. Tapi jika arah itu menjauh dari kebutuhan dasar, maka program tersebut kehilangan legitimasi moral dan sosial. Pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya kepala daerah, perlu mengevaluasi ulang arah pembangunan. Rakyat tidak butuh kecepatan semu. Mereka butuh substansi, keberlanjutan, dan kebijakan yang menyentuh hidup mereka dari dekat.
Jika 100 hari ini gagal menjadi fondasi yang kuat, maka sisa masa jabatan hanya akan menjadi pengulangan pola lama: penuh janji, miskin realisasi.
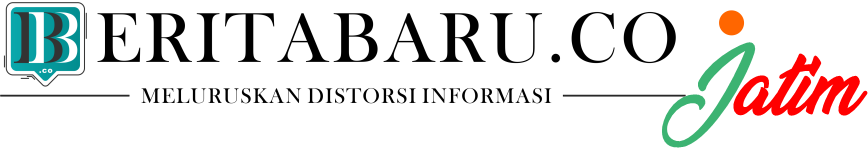
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co






