
Meninjau Kembali Demokrasi Kita
*Syaiful Anam (Pengurus Besar PMII)
DEMOKRASI di Indonesia menjadi penanda penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial dan politik, setidaknya 25 tahun pasca-reformasi. Terdapat beberapa babakan di dalam perjalanannya. Setelah pasang surut dari orde lama ke orde baru dengan model kepemimpinan yang despotis dan otoriter. Pasca-reformasi menjadi harapan baru bagi terwujudnya transformasi sosial, politik, dan ekonomi. Tetapi, setiap zaman memiliki coraknya tersendiri. Menggambarkan inovasi, stagnasi dan polarisasi di dalamnya. Hal ini adalah konsekuensi dari keterbukaan dalam sistem demokrasi. Kebanyakan, ia selalu berhubungan dengan model kepemimpinan, kekuatan politik yang dominan, serta kontrol ekonomi kelas tertentu. Ketiganya memberikan dampak yang luas terhadap bentuk kemajuan di satu sisi dan dekadensi di sisi yang lain.
Artikel ini mencoba meninjau kembali kondisi proses demokratisasi yang berlangsung. Apakah negara cum pemerintah ini berhasil dalam memajukan ‘demokrasi’ setelah capaiannya keluar dari keterpurukan di Era Soeharto dengan bertumpu pada dalih menguatnya proses konsolidasi demokrasi pasca-reformasi. Tesis tersebut, sampai saat ini menjadi pola pandang yang dominan di kalangan para analis. Kerapkali, Zaman Orde Baru menjadi titik perbandingan bagi keberhasilan demokratisasi pasca-reformasi. Tanpa memberikan refleksi-analitis terhadap keberlangsungannya saat ini. Refleksi yang dimaksud adalah memberikan perhatian lebih pada dua dekade perjalanannya dengan pelbagai dimensi yang ada di dalamnya. Hanya dengan kondisi yang benar-benar demokratis kita bisa melihat dengan jernih bagaimana situasi demokrasi kita.
“Bila otoritarianisme adalah jahitan membutakan di pelupuk mata, maka demokrasi adalah momentum terbebasnya penglihatan sehingga dengannya kita mampu menatap dunia. Namun persis ketika mata terbuka dan hamparan dunia tercecap, seluruh persoalan kemudian terbentang menjadi milik kita” (Robet, 2021, p. 95).
Kendati demikian, demokrasi di sisi yang berbeda terdapat kabut membutakan mata kita untuk melihat segala persoalan dengan jernih. Besarnya kuasa elit dengan relasi patronase, kuasa hegemoni politik, dan despotisme dalam bentuk lain adalah jahitan baru perlahan menyeret kita pada kealpaan. Jika dan hanya jika dalam kemungkinan keterbukaannya yang vulgar kita dapat menyelami beragam persoalan yang berada di dalamnya. Sebab demikian lah, kesadaran kolektif civil society menjadi dasar dari mode of being (modus eksistensial) demokrasi.
Demokratisasi di Indonesia bisa dilihat melalui dua perspektif utama yakni komparasi dan lokalitas. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh Jamie S. Davidson dalam bukunya Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru (2022). Studi komparasi memungkinkan kita melihat proses demokratisasi Indonesia dari luar. Perbandingan dengan upaya demokratisasi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Demokrasi di Indonesia menunjukkan daya tahannya. Reposisi elite dalam jabatan-jabatan di sektor pemerintahan berjalan dengan mulus, dan sebagian besar rakyat di Indonesia memandang pemilu berjalan dengan baik. Tesis ini tentu saja terkesan ‘begitu adanya’ apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Filipina yang menghabiskan 13.000 nyawa. Padahal Filipina merupakan negara dengan demokrasi yang lebih tua dibandingkan dengan Indonesia.
Sementara di Malaysia, Perdana Menteri Najib Razak tertuduh menyalahgunakan kekuasaan dengan menggelapkan uang negara sebesar lebih dari US$ 700 juta. Sejak tahun 1950-an sampai 2018 partai terbesar yakni United Malays National Organization (UMNO), berkuasa di parlemen. Dibandingkan dengan situasi ini, Indonesia jauh lebih baik. pasca-Soeharto belum ada presiden yang terkena kasus demikian, kecuali Presiden Abdurrahman Wahid yang dimakzulkan dengan tuduhan melakukan korupsi meski sampai saat ini tuduhan tersebut belum terbukti sama sekali.
Vietnam dan Thailand juga tidak lebih baik dibanding Indonesia. Di Vietnam tidak ada pemilu di tingkat nasional dan sampai saat ini pemerintahan tersentral dalam kuasa satu partai tunggal. Thailand justru menunjukkan demokratisasi di negara tersebut tidak berjalan sama sekali. Militer memiliki andil yang sangat besar. Hal itu terlihat ketika situasi politik tidak dapat diatasi. Di negara Gajah Putih tersebut ada hukum yang terkenal kejam yaitu ‘Hukum draconian’ membungkam suara-suara kritis dan diberlakukannya hukum lese majeste kerajaan; memberikan kekuasaan nyaris absolut pada junta yang memegang kendali pemerintahan saat ini.
Myanmar kendati memulai proses transisi menuju demokrasi—sikap yang membuat negara-negara demokrasi di dunia terkejut melihat pergeseran tersebut— negara sangat mengisolasi diri itu perlahan membuka diri. “liberalisasi politik telah memicu bentuk nasionalisme buddhis yang mengakibatkan pembunuhan ribuan muslim Rohingya dan pengusiran ratusan ribu lainnya dari provinsi asal mereka di bagian barat negara” (Davidson, 2022).
Di Indonesia kita belum menjumpai kasus serupa yakni pembantaian terbuka terhadap penganut agama tertentu oleh agamawan yang paling merasa nasionalis. Islam sebagai agama dengan pemeluk terbanyak, di Indonesia tampil dengan ekspresi sosial-politik yang beragam. Tetapi nyaris praktik ultra-nasionalis yang bersandarkan pada identitas keagamaan tertentu tidak dapat dijumpai serupa dengan kasus di Myanmar. Kondisi demikian, bukan berarti menempatkan Indonesia adalah negara paling demokratis di Asia Tenggara.
Demokrasi selalu bersifat inter-relasional dengan kondisi lokal. Asumsi utama dalam tesis meninjau demokrasi dari wajah lokalitas di Indonesia tentu saja akan memunculkan hasil yang berbeda. Dengan mengalihkan pandangan dari perspektif komparatif yang luas ini ke sudut pandang lokalitas yang spesifik, sebagian pendar demokrasi Indonesia sirna (2022, p. 5).
Negara dengan lanskap maritim ini memiliki banyak problem yang bersangkut-paut dengan jatuh bangunnya proses demokratisasi. Kita dihadapkan dengan banalitas sebuah rezim kekuasaan yang tidak tuntas dalam banyak hal. Seperti melemahnya Lembaga pemerintahan akibat campur tangan berlebihan sekelompok elit kuasa, jomplangnya kesejahteraan akibat tiadanya kesetaraan yang ideal.
Ketimpangan yang semakin meningkat, lambatnya pengentasan kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan kerap kali muncul di ranah publik, dan eksploitasi sumber daya alam yang menguntungkan sekelompok minoritas berakibat semakin mencuatnya problem eksklusi sosial.
Demokrasi dalam praktiknya kini justru lebih banyak dipakai sebagai kendaraan impunitas bagi para koruptor dan apa yang disebut Bung Hatta sebagai benefiter. (2021, p. 101) Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan semakin meningkat. Rentannya kelompok perempuan di sektor privat dan publik disebabkan oleh faktor yang kompleks. Kenyataan itu menunjukkan betapa abainya negara terhadap terhadap hak minoritas.
“Komnas Perempuan pada Januari s.d November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal” (Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan terhadap Perempuan (25 November-10 Desember 2022).
Tingginya angka kekerasan ini ditopang oleh kompleksitas problem perempuan di hadapan kekuasaan yang superior. Relasi perempuan dan kelompok rentan lainnya dengan kekuasaan negara tidak setara. Negara dengan instrumen kekuasaanya menempatkan diri sebagai subjek superior sedangkan perempuan –sebagai tubuh sosial— adalah subjek pasif; kerap kali menjadi objektivitas dari banalitas kekuasaan yang dispotik. Relasi ini idealnya harus didekontruksi ulang. Menempatkan perempuan sebagai subjek aktif yang setara. Bebas mengartikulasikan hak dan posisinya dalam pengarusutamaan demokrasi di Indonesia.
Sisi kelam proses demokratisasi di Indonesia—sebagai sebuah trajektori politik— kerapkali diartikulasikan oleh elitisme kekuasaan. Melalui serangkaian doktrin yang eksklusif, aparatus negara beserta instrumen ideologisnya. menerapkan apa yang disebut dengan politik orwellian—sebuah adagium politik yang populer di abad 20 diambil dari ‘novel 1984’ gubahan Orwell— Melakukan kontrol hampir disemua ruang di mana kritisisme publik itu harus dikemukakan.
Dalam perjalanannya, Indonesia melakukan liberalisasi politik yang semu. Memberikan kebebasan melakukan kritik demi meningkatkan kualitas demokrasi tapi secara bersamaan kekuasaan mengontrol bagaimana kritisisme dilakukan, dalam artian ada batasan-batasan tertentu yang kerap kali disandarkan pada persoalan moralitas kehidupan bernegara.
Tetapi di sektor ekonomi, prinsipnya berbeda. Reformasi ekonomi Indonesia menggantungkan dirinya pada investor sebagai pelaku utama, baik domestik maupun investor asing. Seperti kasus ekstraksi sumber daya alam yang terus berlangsung saat ini. Logika pembangunan yang didasarkan pada akumulasi kapital dan/atau pertumbuhan ekonomi tidak mempedulikan keberlanjutan daya dukung ekologis.
Akibatnya adalah munculnya sektor eksternalitas; kerugian yang harus ditanggung sendiri oleh masyarakat yang terkena dampak. Kondisi demikian paralel dengan apa yang disebut sebagai “rezim-rezim ekstraksi” (Li & Semedi, 2022). Li & Semedi, memaparkan bawah ciri mendasar rezim ekstraktif yang telah mengakar di Indonesia sejak 1966 adalah adanya kemampuan pejabat pemerintah, politisi, dan kroni swasta mereka mengeruk apa pun semaunya karena mereka bisa. Kekebalan mereka “mapan” dalam arti sudah berakar ke mana-mana, dilembagakan, dan diatur secara hirarkis: semakin tinggi jabatannya diharapkan semakin besar daya keruknya (2022, p. 31).
Dalam kasus ekstraksi batubara, hampir tidak pernah luput dari keterlibatan para elit politik. “Kebutuhan terhadap modal yang besar, keterkaitan erat dengan peraturan pemerintah, adanya royalti dan pajak serta ketergantungan terhadap infrastruktur pemerintah untuk mengirimkan batu bara ke pasar menjadikan sektor ini terpapar korupsi politik, dalam bentuk perdagangan pengaruh, political capture dan regulatory capture.
Perusahaan pertambangan batu bara harus berurusan dengan pejabat publik, yang kemudian mendorong “perselingkuhan” antara perusahaan, birokrat, dan politisi. Para elit politik juga menyatukan bisnis dengan politik di sektor pertambangan batu bara (JATAM, 2018). Kerusakan ekologis berhubungan dengan paradigma pembangunan yang mengedepankan surplus ekonomi makro dan mensubordinasikan hak-hak lingkungan hidup. Dalam banyak kasus lingkungan, kerpakali negara menjadi penopang utama aktivitas ekstraksi sumber daya alam.
Tiadanya model demokratis yang mewadahi keberlanjutan ruang hidup ditambah kuatnya intervensi kalangan oligarki yang predatoris terhadap sumber daya, menimbulkan kesemrawutan tata kelola sumber daya alam. Itu lah yang disebut dengan ‘kenyataan hukum besi oligarkis’.
Kita semakin pesimis dengan tesis bahwa demokrasi sebagai obat mujarab bagi semua penyakit. Pada kenyataannya, saat ini, Demokrasi menjadi berkah bagi sebagian kalangan, tetapi kutukan bagi yang lain. Rantai kekerasan semakin bertambah dalam sistem demokrasi yang didominasi oleh elit oligarki. Akhirnya, kita menyaksikan betapa setiap orang melihat dan mengalami demokrasi dari posisinya masing-masing. Bagi kalangan yang dilemahkan hak-haknya, demokrasi ibarat selubung malam pekat yang memaksanya untuk bergerak tidak beraturan.
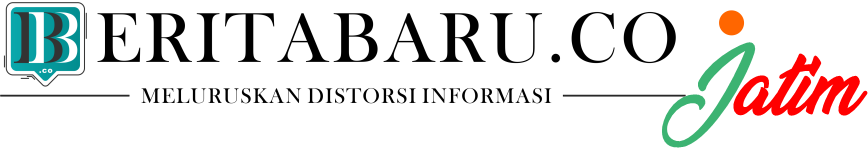
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co






