
Bukan Juragan | Cerpen: Sheillah Aunillah
Mentari masih tertidur bersama nelayan-nelayan yang kelelahan selepas tampil di tengah lautan. Mereka memilih berangkat di pagi hari karena sekarang memasuki musim hujan. Aku pun begitu. Tetapi, setelah sengaja meninggalkan kail dan pancingku di teras rumah saat melihat mereka sedang bergulat di ruang tengah, aku memilih untuk mabok saja daripada harus melaut dengan menahan amarah. Dasar kaji edan!
Bagaimana bisa mereka sampai pada titik itu? Sementara lamaran H. Kadir -juragan kapal- sudah ibu tolak minggu kemarin. Apakah kejadian itu terulang lagi? Sudah berapa kali ibuku ditipu dengan janji manis bos-bos kapal yang ingin melamarnya dengan kedok membebaskan hutang-hutang mendiang bapakku yang sampai sekarang belum juga terpenuhi. Untung saja aku berani meninju wajah brewoknya saat mereka mencoba membawa kabur surat tanah dan warisan lainnya milik bapak yang masih tersimpan di lemari kamar.
Sudah dua kali ibuku menolak lamaran mereka yang ternyata hanya ingin memanfaatkan warisan ibu yang didapat dari bapak dan mbahku. Meskipun bapakku meninggalkan banyak hutang, tetapi hidup kami jauh lebih bahagia dan tenang. Bapak juga berusaha untuk melunasi hutang-hutang itu sebelum jasadnya yang telah membusuk ditemukan mengapung di samping sampannya yang berlubang. Aku juga tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Jika karena hujan saat bapak di tengah laut, itu dapat dipercaya. Tetapi, mengapa di punggung bapak terdapat luka seperti itu, yang kata orang-orang, barangkali terbentur karang. Aku masih belum ikhlas menerima ini semua. Aku ingin bapak kembali. Hingga ibuku tak perlu lagi didekati banyak juragan kapal yang hatinya batu namun kepalanya berisi uang.
Aku sementara meninggalkan rumah itu, rumah warisan bapakku. Meskipun gelap, ini sudah pagi, pukul dua lebih tiga menit. Bahkan ujung jari-jari kakiku telah keriput dan mengeluh dingin akibat kubiarkan mencicipi asin dan dinginnya air laut di tepi pelabuhan ini. Oh, rupanya perempuan itu masih mencariku. Si kembang desa, bahkan sudah janda beranak dua. Suaranya yang terus berteriak memanggil namaku bak mencari orang hilang di tengah hutan itu semakin dekat, kemudian jauh dan tak terdengar lagi. Barangkali lelah karena putranya ini bertelinga tebal. Aku menghiraukannya sembari melanjutkan menenggak ciu yang masih tersisa setengah botol lagi.
Aku Kholis, kakakku sudah menikah dan ia tidak peduli lagi dengan aku dan ibuku yang masih tinggal di desa pinggir tambak ini. Ia tak pernah sekali pun datang berkunjung, kecuali saat lebaran. Hanya datang, cium tangan, lalu kembali pulang setelah menghabiskan satu stoples bipang. Barangkali kehidupan dia lebih mapan. Keseharianku tidak lain dan tidak bukan hanya melaut dan setor ikan. Dengan sampan mendiang bapak yang pernah lubang di bagian depan. Harus dikuras lebuh dulu agar aku tidak tenggelam di tengah lautan.
Malam itu, aku sedang mencari tengkulak bipang untuk dijual saat Haul Mbah Hamid minggu depan. Seperti biasa, aku dan ibuku berjualan potongan buah nangka dan bipang sebagai buah dan makanan khas Kota Pasuruan. Lumayan, hasilnya bisa dipakai untuk makan satu pekan. Daripada hasil setor ikan, Cak Sur sudah memotongnya sebagai biaya hutang kapal, sehingga hanya cukup untuk makan tiga hari. Kami tak akan bisa melaut jika kapal hasil hutang itu diambil lagi. Sedangkan kami akan kelaparan jika tak melaut lagi. Namun, setelah melihat juragan itu memegang tangan ibuku sedangkan ibuku hanya bisa diam dan menahan tangis, aku jadi emosi, bukan sedih. Aku tak mau memberi bogem mentah untuk yang kedua kalinya, sehingga aku memilih kabur dan berakhir merenung di tepi pelabuhan ini.
Tiga tahun setelah bapak tiada, kehidupanku bersama ibuku menjadi berantakan. Meskipun hampir kepala empat, ibuku masih saja bergetar pinggangnya ketika melihat seorang pria kekar yang turun dari kapal untuk rehat setelah tampil sepanjang malam di tengah lautan. Sudah dua kali aku memergokinya bersama juragan kapal dari desa sebelah dan bosku sendiri ketika aku pulang melaut. Setelah aku kembali ke rumah, ada orang lain lagi, ini yang ketiga kalinya. Kali ini sedikit berbeda. Aku tak menemukan gelagat mencurigakan dari orang itu. bajunya selalu rapi, bersih, dan sering berjamaah di musala. Aku sedikit mempercayainya karena ia perlahan menuntun ibuku agar tidak terlalu terbuka pada lelaki dan sekarang malah berjilbab tiap hari. Ah, aku lupa namanya, ibu hanya menyuruhku memanggilnya dengan sebutan ayah atau abah. Aku memilih abah.
Abah setuju ketika kuajak berjualan bipang dan nangka saat Haul Mbah Hamid di sekitar area Pondok Salafiyah dekat alun-alun kota. Tetapi, ibuku menolaknya dengan alasan agar dirinya saja yang berjualan, sehingga aku bersama abah dapat mengikuti serangkaian acara haul. Kami setuju. Pagi-pagi sekali kami berangkat, bukan pagi, tetapi masih dini hari. Menata dagangan di atas amben kemudian melayani pembeli dari pengunjung luar kota yang sudah berdatangan bahkan sampai tidur di emperan jalan. Siapa yang ingin melewatkan acara haul sang waliullah yang sangat kharismatik dan disegani di berbagai wilayah ini. Para masyarakat dari dalam dan luar Kota Pasuruan, para kiai, ulama, santri, bahkan pejabat turut datang dan membanjiri pusat kota untuk merayakan Haul Mbah Hamid.
Setelah mengikuti maulid di dalam area pondok, aku berpencar dengan abah. Naluri copet masih menggelora di dalam diriku jika berada di keramaian seperti ini. Aku tak ingin abah tau akan hal ini. Ini tahun ketiga aku mengikuti haul sekaligus mencari puing-puing pendapatan selain dari jualan nangka dan bipang. Lumayanlah, satu atau tiga unit telepon genggam untuk kebutuhan membeli beras dan syukur-syukur bisa makan dengan lauk sate komo.
Aku berjalan pelan, bahuku bersentuhan dengan pengunjung lain. Semua orang di pusat kota saling berdesakan. Mereka antusias mengikuti acara Haul meskipun tidak kebagian tempat dan berkat. Yang kusukai dari acara ini selain peluang untuk mencopet yaitu cuacanya tidak begitu panas dan sedikit mendung. Sejuk. Barangkali langit sedang tunduk pada sang wali, ia tak berani menampakkan mentari sepanjang acara Haul selama dua hari.
Berhimpitan seperti ini merupakan peluang bagiku. Aku bisa meraba saku baju koko seorang remaja berpeci hitam yang dapat kujangkau dengan tangan. Hap! Kosong. Baiklah, barangkali anak ini menyimpan telepon genggamnya di tas kecil itu. Jikalau begitu aku hanya perlu membuka sedikit resletingnya dan ya, benar saja. Satu unit kuamankan. Aku menyimpannya di saku bagian dalam jasko -jas koko- milikku pemberian abah.
Aku terus berjalan pelan agar selalu berdesakan dengan pengunjung lain. Jarak dari gang pondok ke tampat ibuku berdagang kurang lebih 600 meter lagi, sedangkan orang-orang ini memenuhi jalan hingga ke terminal lama, 1 km dari alun-alun. Aku menemukan celah di bagian sampingku. Seorang wanita berjubah hitam yang memakai ransel. Kesempatan ternyata bisa datang dua kali. Aku berpura-pura terdorong agar sedikit menyenggolnya. Ia menoleh sekilas, aku meminta maaf. Setelahnya tanganku mencoba untuk membuka resleting bagian sampingnya, hanya ada tisu dan uang receh. Barangkali ada di bagian depan.
Belum sampai tanganku membuka resleting bagian depan tasnya, seorang pria botak di depan sana berteriak, tangannya menunjuk ke arahku. “Copet!! Copet!!” Aku amat sangat terkejut. Apakah aku ketahuan?
Wanita ini refleks berputar menghadapku dan memindahkan tasnya ke depan dada lalu mendekapnya. Pria botak terus saja berteriak dan menunjuk ke arahku. Orang-orang memusatkan pandangannya kepadaku. Aku membatu. “Itu dia! Dia lari, dia lari! Kejar dia!”
Lari? Aku tidak lari.
Beberapa lelaki ikut berlari ke arahku. Tetapi, aku hanya dilewatinya. Aku bingung hingga keringatku mengucur. Pandanganku tetap ke pria botak itu. Ia tidak ikut berlari karena memang jalan sedang penuh. Beberapa lelaki di sekitarku tadi langsung putar balik dan mencari celah untuk mengejar si copet.
“Mas, tolong bantu kejar, kasihan bapak itu, dompetnya diambil.”
Aku tersadar. Aku harus membantunya. Ternyata pria botak tadi yang dompetnya dicopet. Dasar pencopet cupu. Barangkali dia baru belajar. Aku harus ikut mengejarnya meskipun aku termasuk ke dalam golongannya. Tak apalah, barangkali pria tadi memberiku imbalan jika aku berhasil menangkap copet itu.
Aku ikut berlari bersama beberapa lelaki lainnya. Sampai di ujung gang, aku menemukan si pencopet yang memakai baju koko dengan jaket beserta sarung hijau polos. Ia berusaha menyelinap ke arah pengunjung yang sedang menyantap kupang. Aku seperti mengenalinya. Tetapi, banyak di antara orang-orang yang berpakaian sama dengannya, hanya gelagatnya yang berbeda. Aku paham, ia sedang berkamuflase agar tak menarik perhatian. Sebelum beberapa lelaki itu berhasil menangkapnya, aku lebih dulu berada di belakang copet itu dan menarik kerah belakang baju kokonya. Si copet yang baru saja ingin menunduk untuk menyembunyikan dirinya di antara rombongan orang Arab berkulit hitam, aku lebih dulu menariknya kembali dan memberi instruksi pada orang-orang bahwa akulah yang berhasil menangkap copet itu.
Hap! Si copet menoleh, aku mengacungkan sebelah tanganku tinggi-tinggi. Saat aku menatap wajahnya, aku terkejut bukan main. Kami beradu pandang. Aku tak asing dengan wajahnya. Aku membisu dan tak dapat memberi instruksi bahwa si copet telah tertangkap. Benarkah ini dia? Tiga detik kemudian, beberapa lelaki dapat melihat kami dan langsung menghajar si copet. Entah kenapa aku tak bisa menyumbang beberapa bogeman seperti yang mereka lakukan padanya. Aku merasa kasihan dan ingin menolongnya. Namun, lagi-lagi aku hanya bisa membisu. (*)
Sheillah Aunillah, lahir di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Saat ini menempuh studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Jember. Sibuk apa saja, yang penting menulis.
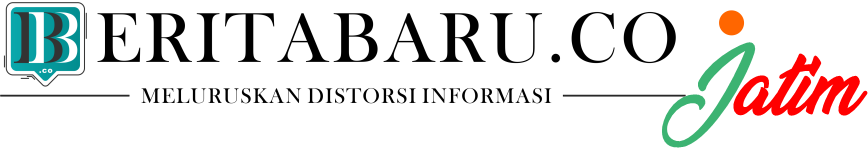
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co





