
Semangkuk Jenang Sapar Buatan Emak| Cerpen Cindy Virda Amelia Dewi
Hari itu menjelang sore, langit barat mulai didominasi warna kemerahan di langit. suasananya cukup aneh, seperti ada suasana tidak nyata, tak tersentuh. Angin yang berembus terasa menusuk, tapi tak benar-benar membuatnya kedinginan.Aneh, situasi ini seperti berada dalam kotak kosong tanpa udara, menekan sekaligus membuat terombang-ambing.
Kursi kayu rapuh yang didudukinya berderit ketika tubuh itu sekonyong-konyong berdiri sambil menutupi mulut, seakan ada sesuatu yang keluar akan dari sana. Berlarilah ia ke teras dan memuntahkan sesuatu, benda putih padat jatuh ke tanah dibarengi dengan tetesan darah segar. Ada rasa sakit yang nyata baginya, tak hanya area gusi tapi nyerinya menjalar ke kepala, parahnya ada rasa sesak di dadanya. Bukan, tidak ada masalah pada jantung atau pernapasan, tetapi rasa sesak seperti batu besar menimpa tubuhnya.
Bulir keringat sebesar biji jagung menetes di pelipis, napasnya memburu. Perempuan itu menyibakkan rambut panjangnya. Terduduk di lantai dengan rasa cemas yang entah datang dari mana. Kedua mata mulai menggelap tapi jantungnya berpacu entah berapa kali lipat. Gendang telinga menangkap suara sayup-sayup yang berusaha untuk dikenali, dalam beberapa detik tubuhnya tersentak dan kedua mata terbuka lebar.
Sarung bantal di kepalanya basah, selimut entah ke mana, menyisakan dirinya dengan baju tidur ala kadar dengan keringat dan gemetar di sekujur tubuh. Mimpi itu hadir dua kali, terakhir seminggu yang lalu. Ia tidak pernah memikirkannya, tetapi dua kali?
Meraih ponsel yang berdering, ia melihat nama kakak ipar. Diusap pelan permukaan layar dan menempelkan ke telinga. Suara letih dengan napas putus-putus berusaha menyampaikan sebuah kabar.
Risa, Emak masuk rumah sakit, dia jatuh di rumah. Sekarang ada di ICU, Masmu sedang menemani di dalam.
Rangkaian kalimat itu berputar seperti kaset rusak di dalam otaknya, berulang-ulang tanpa lelah membuat Risa tenggelam dalam ketakutan di atas bus selama perjalanan pulang. Sebelum berangkat, ia sempat mengabari atasan, rekan kerjanya—Arban—mendesak akan menemani pulang, tapi Risa mengatakan tidak perlu. Setelah membalas pesan singkat tersebut, ia menutup ponsel dan melemparkan pikiran pada “seandainya” yang diangan-angankan.
Seandainya dua hari lalu atasannya setuju memberikan cuti, mungkin Risa sudah ada di rumah bersama Emak. Ia tahu betul, pasti Emak sibuk membuat bubur sapar dan nasi kuning untuk menyambut anak-anaknya pulang. Sejak Risa dan Masnya masih kecil, setiap memasuki bulan Safar, Emakselalu menghidangkan jenang grendul dan nasi kuning. Sebagai simbol tolak bala, katanya.
“Kan kita tinggal berdoa kepada Tuhan, Mak, untuk meminta perlindungan. Kenapa harus bikin jenang? Kan capek.” celetuk Risa kecil.
“Membuat jenang dan nasi kuning adalah bentuk kesungguhan dari permohonan kita kepada Tuhan untuk meminta perlindungan. Jadi, tidak hanya doa. Justru dengan membuat jenang, membentuk tepung ini menjadi bulat-bulat kecil satu persatu, adalah bentuk kesabaran dan keyakinan kita dalam berdoa kepada Tuhan.”
“Semua orang membuat jenang juga, Mak?”
“Tidak semua orang. Tradisi menyambut bulan Safar dengan membuat jenang grendul ini kebanyakan dilakukan oleh orang Jawa saja. Tradisi ini sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu, karena tujuannya baik, kan? Untuk membuktikan kesungguhan kita berdoa kepada Tuhan.”
“Oh, begitu. Nanti kalau Risa sudah besar, akan membuat jenang grendul untuk Emak dan Mas Danu.”
Begitulah penjelasan dari Emak pada Risa agar mudah dipahami oleh anak seusia enam tahun. Mereka berdua berjibaku pada adonan yang masih cukup banyak untuk dijadikan jenang. Mas Danu yang lebih tua tiga tahun darinyasedang membakar dedaunan di halaman belakang rumah, mengeluhkan api tidak kunjung menyala. Bapak sudah meninggal sejak Risa masih bayi, bayangan akan sosok Bapak tidak pernah ada pada memori otaknya. Ia hanya tahu rupa Bapak dari foto, dan cerita Emak yang mengatakan bahwa suaminya adalah orang yang sangat baik.
Sehabis magrib, ketiganya menikmati jenang grendulbersama setelah melantunkan doa bersama. Manis kenyal bulatan jenang dari tepung ketan itu sangat nikmat bagi Risa. Dipadukan dengan santan yang dimasak dengan daun pandan menambah rasa gurih dan wangi, kombinasi rasa dan aroma itu melekat di diri Risa.
“Risa sangat suka jenang grendul buatan Emak. Di antara semua jenis jenang, cuma jenang ini yang Risa suka,” katanya dengan riang penuh senyum.
“Halah, kamu kan memang suka makan. Jadi semua makanan kamu suka!” celetuk Mas Danu.
“Apa sih, Mas? Memang masakan Emak itu enak,” balasnya ketus sambil membuang muka.
“Kalau begitu, setiap tahun Emak akan membuatkan jenang sapar untuk kalian berdua.” Emak tersenyum lebar, senyum yang selalu menghangatkan hati anak-anaknya.
Sejak saat itu Risa dan Danu sepakat untuk pulang setiap memasuki bulan Safar.
Sepanjang jalan Risa berdoa untuk keselamatan Emak. Ia berharap rasa jenang grendul dan nasi kuning akan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang mereka lewati bersama.
Berjam-jam berkelana menjelajahi kepingan memori masa kecil bersama Emak dan Mas Danu, bus sudah siap masuk ke terminal dan berhenti untuk menurunkan penumpang. Risa menggendong tas punggung dan memeriksa ponsel, satu pesan baru. Masih dari orang yang sama, kakak iparnya.
Risa, langsung pulang ke rumah saja.
Dada Risa seperti dihantam batu besar, air matanya sudah tidak terbendung. Ia mengumpulkan kekuatan untuk sekadar mampu turun dari bus yang berdesakan dengan orang-orang. Dipijakkan kedua kaki di tanah kelahirannya, terasa berat dan tubuhnya gemetar. Risa menepi, duduk di pinggiran taman yang dicor cukup tinggi. Dikeluarkannya air mata yang sudah tak bisa ditahan di pelupuk.
“Risa! Risa!” Sebuah suara menghampiri telinga disertai tepukan kecil di pundak. Sesosok pria berjongkok di depannya. “Ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit.”
“Arban? Emak! Emak sudah di rumah, dia tidak di rumah sakit. Aku harus bagaimana?”
Dalam sepersekian detik pria itu mencerna perkataan Risa, ia tidak berani mengungkapkan pikiran. Arban hanya bisa membantu wanita itu berdiri dan berjalan untuk mencari tumpangan selanjutnya.
Kilo demi kilo panjangnya jalan terlewati, membelah riuh kendaraan dan matahari yang terik di luar mobil. Keduanya tidak berbicara, satu tenggelam pada kekalutan, satunya lagi tenggelam pada pikiran bagaimana cara membuat Risa merasa lebih baik. Jawaban atas pertanyaan Arban tidak ditemukan hingga mobil berhenti tepat di sebuah rumah yang diramaikan oleh beberapa tetangga.
Tanpa memedulikan apa pun, Risa segera menghambur keluar meninggalkan Arban yang masih mengurus ongkos kendaraan dan membawa tas bawaan mereka berdua.
Selangkah lagi untuk naik ke teras rumah, ia disambut oleh Mas Danu dengan wajah sembab dan merah. Di belakangnya, tergopoh-gopoh wanita muda memanggil nama Mas Danu, istrinya.
“Baru pulang kamu? Baru pulang setelah Emak tiada?” Nada bicaranya tinggi, emosinya meluap pada sang adik yang melinangkan air mata—lagi.
“Risa mau lihat Emak, Mas! Emak di mana?”
“Kita sudah sepakat akan bersama-sama pulang, Risa. Untuk Emak!
“Aku pulang untuk Emak, Mas. Atasanku nggak kasih cuti, makanya aku nggak bisa pulang cepat. Tapi aku terus mengusahakan.”
Istri Mas Danu menyodorkan segelas air untuk suaminya agar lebih tenang. Pasalnya, pertengkaran mereka terjadi di teras rumah, disaksikan oleh para pelayat. Mereka mulai melontarkan bisik-bisik, mengatakan bahwa kedua anaknya yang hidup mewah di kota tidak pernah peduli pada Emaknyadi desa.
Mas Danu meraih gelas berisi air tersebut, alih-alih meminumnya, justru ia banting gelas tersebut hingga pecahannya menyambar kaki Risa. Dengan darah yang mulai keluar dari luka, Risa menerjang masuk dan mencari Emak. Tubuh itu terbujur kaku di atas meja menghadap ke utara, lengkap dan berselimutkan kain batik.
Anehnya, air mata Risa seperti habis. Ia hanya merasa tubuhnya sangat lemas hingga luruh ke lantai. Dua tangan kokoh sigap menopang tubuh Risa agar tidak terbentur ke lantai. Kesadaran Risa tidak hilang sepenuhnya, tetapi pandangannya dipenuhi oleh adegan masa kecil bersama Emak. Kini, tubuh Emak sudah kaku tidak bernyawa. Sialnya, Risa tidak memiliki kesempatan terakhir untuk bicara.
Beberapa jam setelah prosesi pemakaman, mereka kembali ke rumah. Hanya ada beberapa kerabat dekat yang menemani mereka menyiapkan makanan untuk acara tahlil tujuh hari ke depan. Risa duduk di kursi yang menghadap meja makan kecil sederhana, menatap sebaskom jenang grendul dan santan di wadah terpisah.
Tangannya yang gemetar mengambil mangkuk kecil dan mulai menyendok butiran jenang lengket tersebut, kemudian menyiramkan santan. Sesuap masuk ke mulut, rasa manis menyeruak, bersama dengan senyum Emak yang kembali muncul di ingatan. Santan yang putih bersih itu ternyata sudah mulai basi, seakan mengingatkan diri bahwa hidupnya tanpa Emak akan menemukan banyak kebasian yang lebih banyak.
*
Celemek warna biru muda yang menempel ditubuh Risa lepaskan dan digantung di dekat kompor. Diangkatnya wadah berisi bulatan kenyal berwarna hijau kemerahan dari tepung ketan menuju meja makan. Sudah ada empat mangkuk kecil yang siap di empat kursi kosong. Risa mengecek ponsel, membuka pesan baru, lalu membalasnya dengan pesan suara.
“Iya, Mas Danu. Aku sedang menghidangkan jenang grendul buatanku. Istrimu buat juga nggak? Pasti rasanya lebih enak punyaku, hahaha.” Ia tergelak atas perkataannya sendiri.
Pintu rumah terbuka, menampilkan sosok pria yang selalu menemaninya, bertahun-tahun pasca Risa kehilangan Emak. Arban. Dua bocah menyambut pria itu dengan gembira sekaligus raut wajah kesal.
“Papa, lihat Mas Bian nggak mau pinjamkan mainannya untuk Tiara,” rengek bocah perempuan yang menggelayuti lengan sang ayah.
“Sudah-sudah, ayo sini makan jenang grendul,” interupsi Risa pada tiga orang yang mulai beradu argumen. Mereka mulai duduk di kursi masing-masing.
“Mama, jenang grendul ini apa? Kenapa Mama buat makanan ini?”
Risa tersenyum, ia akan bercerita, ia akan mulai menjelaskan seperti cara Emak menjelaskan esensi jenang sapar padanya.
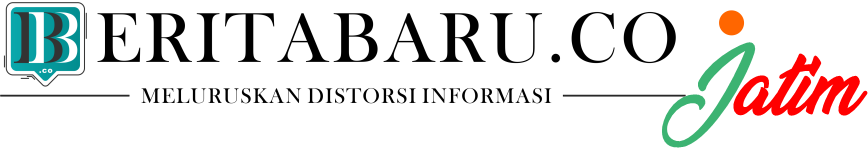
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co







