
Otoritarianisme Modern: Problematika Masyarakat Modern Hingga Perguruan Tinggi Agama
Oleh: Mashur Imam*
“Otoritarianisme Modern”, istilah ini mungkin cukup asing bagi para pembaca yang selama ini melahap banyak buku tentang kepemimpinan politik. Pasalnya, secara epistemologis keduanya berbeda. Otoriter merupakan model birokrasi yang dianggap tradisional dan tidak cocok atau sesuai dengan nalar modernisme. “Kekuasaan harus dilahirkan secara partisipatif dan rasional”, itu kata orang-orang modernesian. Walaupun terminologi dan konsepsinya ambigu, bukan berarti tidak ada. Dalam riset yang dilakukan Freedom House Arch Puddington, melaporkan masyarakat modern juga mengalami penurunan jaminan kehidupan sosial karena otoritarianisme gaya baru yang terjadi di beberapa negara. Temuan ini seolah membuka ruang refleksi bahwa sebenarnya modernisme tidak mengeliminasi otoritarianisme. Otoritarianisme tidak runtuh karena wacana masyarakat modern. Ia tampak tumbuh bersamaan dengan perkembangan gaya rasionalitas baru kekuasaan dan sepertinya lebih menakutkan dalam perspektif psiko-sosiologi. Apalagi kesemua itu terjadi di perguruan tinggi agama yang menuhankan ilmu modern dan juga moral transenden (ilahiah).
Masyarakat Modern dan Kerangkeng Legalitas Kuasa Perguruan Tinggi Agama
Ada beberapa fenomena sederhana yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan munculnya otoritarianisme pada aspek politik. Tidak jarang kita temukan ada ketakutan masyarakat pada pihak yang berwenang dalam segala urusan. Misal ada satu cerita unik di daerah saya. Suatu ketika di salah satu warung kopi di Kabupaten Jember, saya bertemu dengann beberapa orang asal luar kota, sebut saja dari Situbondo. Kebetulan, warung tersebut berada di pinggir jalan. Tempat di seberang kanan, ada spanduk dengan foto bakal colon DPR RI dari salah satu partai besar di Indonesia. Sekitar 20 menit, kita ngerumpi dan diskusi bareng. Tiba-tiba orang dalam foto spanduk itu juga datang ngopi di tempat kami. Tanpa dikomando teman kami berdiri dan berupaya untuk menyapanya. Saya terkejut dan menanyai mereka, “apa kalian kenal?”. Mereka menjawab, “dia kan orang terhormat dan akan berkuasa”. Jadi sang bakal calon DPR tadi, kuasanya telah melebihi waktu bahkan pemilih dapilnya sendiri. Tentunya, kesempatan untuk otoriter juga telah melebihi teritorialnya kewenangannya.
Banyak lagi fenomena lain yang menandakan sumber otoritarianisme bisa muncul dalam ruang politik kapanpun dan di manapun. Pada ruang birokrasi kepemerintahan misalnya, banyak ditemukan petugas layanan masyarakat di kantor kedinasan ditakuti dan dihormati secara ekstrim oleh masyarakat. Satpol PP, satpam, petugas layanan terpadu hingga pembantu pecatatan nikah, bagai penguasa politik dan tokoh agama dalam kehidupan politik masyarakat modern. Mereka ditakuti sebab dianggap berwenang dalam urusannya masing-masing. Walaupun mereka masih petugas layanan dan lapangan. Apalagi pemimpin daerah atau presiden, tentu dalam budaya masyarakat modern pasti dianggap raja dan bebas melakukan apapun. Padahal, kekuasaan mereka dalam perspektif modernisme dilahirkan dari rakyat melalui pemilu. Setelah memimpin atas nama legalitas modern juga, mereka mendapatkan kewenangan untuk bertindak bebas bahkan melanggar hukum sekalipun.
Kondisi demikian dalam kesadaran politik masyarakat modern, telah dianggap lumrah di era ini. Tidak dapat terbantah, kuasa yang telah dilegalkan oleh narasi modernitas, tidak dapat ditolak. Petugas dan pemimpin pemerintahan dianggap pihak yang dapat menyelesaikan masalah hidupnya. Sehingga bagi mayoritas, tidak ada urusan dunia yang mudah tanpa jasanya. Atau dalam bahasa lain, “orang dalam (pemerintah) adalah kunci kesuksesan hidup saat ini”.
Parahnya, kerangkeng legalitas ini tidak hanya terjadi di masyarakat umum. Perguruan tinggi yang merupakan basis pengembangan nalar modernitas, juga tidak dapat mengelak dari habituasi etis demikian. Penghormatan dan ketakutan yang berlebih juga sering terjadi pada sivitas akademika perguruan tinggi. Rektor atau secara umum atasan kampus, seolah menjadi makhluk adi kuasa yang kewenangannya satu level di bawah Tuhan dalam menentukan takdir bawahan akademika, utamanya mahasiswa.
Peter Flaming seorang yang banyak membahas tentang fakta demikian. Civitas akademika menurutnya hidup dalam jejering monarki modern kampusnya. Pada dosen dan tenaga pendidikan bagai mesin yang hanya bekerja pada sistem dan tidak berani melakukan inovasi secara merdeka. Kondisi demikian di Indonesia bukan hanya terjadi di perguruan tinggi umum saja, namun juga perguruan tinggi agama. Beberapa waktu kemenarin, menteri agama Yaqult Choiruddin Qoumas mengancam beberapa rektor yang sewenang-wenang dalam memimpin perguruan tinggi. Ia mengaku punya data tindakan koruptif dan kolusi rektor yang sembrono dalam menjalan kepemimpinannya di perguruan tinggi agama.
Data yang dimaksud sebenarnya telah lumrah terjadi. Banyak rektor PTKI yang telah lama menjalan otoritarianisme modern. Atas nama aturan, mereka kadang juga melanggar aturan. Banyak yang sewenang-wenang pada bawahannya. Beberapa bawahannya, banyak yang diberhentikan jika tidak sesuai satu komando dan perintah. Bahkan ada yang dikorbankan dan terpaksa mengalah karena istri dan anak ingin menjabat di kampus yang ia pimpin. Tindakan-tindakan demikian yang membuktikan tindakan otoriter di era modern, bahkan perguruan tinggi yang bermoral agama sekalipun.
Perubahan Psiko Pemimpin Perguruan Tinggi Agama
Kesadaran masyarakat yang begini, diperunyam lagi dari adanya konsekuensi psikis kuasa itu sendiri. Kekuasaan bukan hanya mendiskriminasi para pengikutnya, namun juga jiwa dari pemegangnya. Saya sering mendengar orang menceritakan teman-temannya yang sukses dengan mengatakan, “dulu sebelum menjabat dia kayak saudara. Setelah menjabat, ya kan sudah sukses, paling ya lupa sama kita”. Perkataan yang hampir mirip, tentu banyak. Secara psikologis, pernyataan tersebut sebenarnya telah membenarkan bahwa para pemimpin dipengaruhi oleh kekuasaannya sendiri.
“Kuasa” paling menarik jika dilihat dari aspek psiko-sosiologisnya. Banyak pakar melihat kekuasaan memiliki efek tersendiri bagi pengetahuan bahkan kesadaran manusia. Pada awal kelahirannya, secara sosiologis, lahirnya dianggap dari keniscayaan adanya interaksi sesama manusia dalam menciptakan soviety yang baik. Tidak heran, jika tokoh terkemuka filsafat, seperti Socrates dan Plato, sudah mendiskusikannya sebagai bagian tak terpisah dari masyarakat. Bukan hanya keduanya, beberapa pakar lain telah memberikan ragam konsep menarik tentang model dan jalan kekuasaan yang ideal. Aristoteles, Weber hingga Marx berbeda-beda dalam menerjemahkan kekuasaan sosial. Walaupun berbeda, mereka para pakar awal, bersenada bahwa kekuasaan itu “diciptakan” bukan “menciptakan”. Pendapat para pakar awal ini, yang disangsikan dalam tinjauan psiko-sosiologis di kemudian hari, yakni tepat di era Postmodern.
Pada era Postmodern, kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai ciptaan keniscayaan kebutuhan sosial namun dapat membentuk sosial dan psikis manusia sendiri. Yang paling masyhur, Antony Giddens. Baginya, kuasa sosial dapat dibentuk dan juga dapat membentuk. Dapat mengontrol dan dapat dikontrol. Dapat memberdayakan dan dapat juga membatasi. Dengan demikian, kuasa tidak lagi ciptaan manusia tapi dapat menciptakan manusia itu sendiri. Tentu, sepintas gagasan ini agak ambigu. Pasalnya, mana mungkin ada makhluk atau sesuatu yang mampu menciptakan penciptanya sendiri? Masak ada roti yang dibuat manusia lalu juga mampu membuat manusia itu sendiri? Tentu tidak ada, namun itulah bedanya roti dan kekuasaan. Kuasa itu dilahirkan manusia untuk menciptakan manusia itu sendiri.
Kekuasaan itu memang unik. Keberadaannya seperti makhluk hidup. Tidak hanya sebagai instrumen sosial namun kadang juga mengubah kehidupan sosial itu sendiri. Bahkan oleh beberapa pihak dianggap sangat menakutkan. Dulu ada penceramah muslim terkenal di Indonesia, KH Zainuddin Mz, dalam pidatonya mensenadakan kekuasasan dengan harta dan wanita sebagai godaan yang mengganggu keimanan. Dalam agama Kristen dijelaskan Injil Lukas 4:1-13 juga disebutkan bahwa kekuasaan sebagai salah satu godaan iman dalam perjuangan Yasus. Jadi, agamawan memandang kekuasaan sebagai godaan dalam kehidupan dunia.
Walaupun pendapat atau ajaran ini bersumber dari agama bukan berarti tidak rasional. Peter Fleming menjelaskan bahwa kekuasaan sangat mempengaruhi psikologi manusia, utamanya di masyarakat modern. Kekuasaan tidak hanya tampil sebagai godaan namun membentuk psikis manusia baik pelakunya maupun partisipan atau pengikutnya. Banyak pemimpin yang sebelum menjabat baik, jujur dan dermawan. Kemudian berubah setelah menjadi makhluk yang paling jahat. Sebenarnya hal ini bukan disebabkan semata karena hasrat subjektifnya sendiri, namun juga karena arus modernisasi telah membingkai kekuasaan dengann sangat magis dan menggoda.
Beberapa kasus seperti pemukulan yang dilakukan keluarga pejabat pajak, penembakan Brigadir J dan lain sebagainya adalah sekian contoh para pengusa tidak tahan pada kekuasaan sendiri. Pada perspektif politik kepemerintahan, kekuasaan telah difungsi kerjakan sebagai posisi pemimpin, pengawas dan pemerintah. Akibatnya, para penguasa terbiasa mengawasi dan memerintah saja, kemudian lupa untuk mengawasi dirinya sendiri. Titik demikian yang menjadi sumber rentannya otoritarianisme tetap lahir di era modern.
Kuasa sebagai sesuatu seksi dan menggoda ini, juga telah terbukti sukses mengubah sikap para pimpinan perguruan tinggi agama. Para rektor PTKI yang sejak lumrahnya telah menyatukan profesionalitas ilmu modern dan ilmu, sama banyak yang tak berdaya digoda kekuasaan sendiri. Kecenderungan kuasa di PTKI juga sama, hanya melatih pemegangnya untuk mengawasi dan memperlemah kesadaran introspeksi diri. Atas dasar legalitas modern yang menurut sudah partisipatif, mereka secara terang-terang menganggap diri lebih berkuasa dari Tuhan. Ia lupa gampang bertindak sewenang dan menilai bahwa seluruh bawahannya bahkan masa depan civitas akademika, termasuk mahasiswa, ada di bawah wewenangnya. Tidak jarang, seorang rektor menabrak aturannya konsensus civitas akademika, berdasar benak bahkan hasratnya sendiri. Demikian ini yang oleh Peter Flaming disebut sebagai “sindrom boss” perguruan tinggi. Mereka merumuskan kebijakan dengan dalih prosedur ilmiah, namun tetap tidak keputusan tetap tidak melanggar kehendaknya. Mahasiswa boleh pintar dan berprestasi, namun urusan konstelasi tetap ngalah pada jaringan, koneksi politik, dan bahkan famili rektor. Semua dosen boleh bagus dalam meneliti, namun dalam kontetasi penelitian, kalau rektor ikut, mereka harus ngalah.
Seluruh fakta ini, banyak ditemukan PTKI di Indonesia. Tidak heran, jika akhir-akhir ini, menteri agama selalu mengungkap nada-nada kesal pada perilaku rektor-rektornya. Semua pihak, utamanya yang bergelut dalam dunia akademik tentu paham pada masalah-masalah tersebut.
* Penanggung Jawab Komunitas Kajian-Penelitian Dar Al-Falasifah, Pengurus LAKPESDAM PCNU Jember, Alumnus Pascasarjana UIN KHAS Jember dan Penulis Buku “Manisto Gerakan; Positioning PMII Jawa Timur Dalam Kontestasi Global”
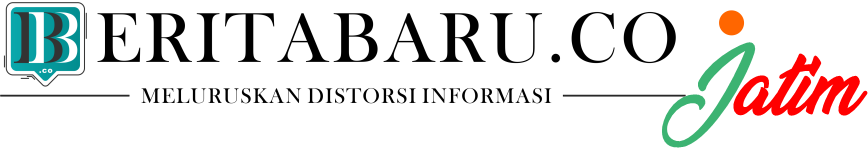
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co






