
Ramadan: Berebut Puasa atau Berebut (Ke)Puasa(n)
Oleh: Dicky Hariyandi
Marhaban ya ramadan, marhaban syahra shiyam, begitu semarak khalayak menyambut bulan ke 9 Hijriah ini. Disokong oleh banjir bandang informasi, ucapan selamat dalam menyambut ramadhan mengisi laman-laman dan beranda media sosial seperti; FB, WatsApp, Instagram dll. komplit sudah rasanya gegap gempita ramadhan merasuk di psikologi publik.
Sudah jadi fenomena umum, tiap-tiap ramadan, jamak hal yang mengalami lonjakan dari etape ke etape berikutnya.
Dalam aspek religius, ramadan adalah rumah inkubator. Ia merupakan momentum dalam mengakumulasi pahala sebesar-besarnya.
Sebab, di bulan ini segenap kebaikan dapat dipanen dengan nilai ganjaran yang dilipat gandakan. Bahkan, tidur orang puasa pun masuk kategori yang dicatat sebagai ibadah.
Tuhan betul-betul menggelontorkan derma pahala secara kolosal untuk setiap kebajikan yang diamalkan seorang hamba.
Ritual puasa yang dilakoni sebulan penuh adalah piranti ubudiyah yang istimewa bagi kaum muslimin. Puasa merupakan madrasah diri dalam mematangkan kehambaan seseorang. Atau dengan idiom lain, puasa adalah bengkel spiritual sebagai upaya penempaan untuk menajamkan kepekaan ruhaniyah.
Persis, ketika posisi berada diantara dua bulan sabit: bulan sabit memasuki ramadhan hingga bulan sabit memasuki syawal, kita harus merubah pola kebiasaan makan. Selama sebulan kita dipaksa bertahan dalam kondisi lapar dan haus siang hari.
Ini sesuai dengan asal kata bahwa shiyam dalam idiom Arab adalah menahan. Dalam syair Arab disebutkan, khoilun shaimun khoilun ghairu shaimatin tahtal ‘ujaji wa ukhra ta’liqul lijama.
Ungkapan tersebut memberi gambaran bagaiamana kuda-kuda disebut shiyam saat manehan diri untuk maju, dan disebut ghairu shiyam ketika ia memacu menerjang musuhnya.
Ketika dikatakan bahwa nafsu yang mewujud sebagai biang keladi lalu dikekang dengan tali kendali, yakni puasa, ungkapan ini memberi makna yang cukup idiomatik.
Nafsu layaknya kuda liar yang harus dikontrol sedemikian rupa. Tak lain agar sifat banalitasnya dapat dijinakkan demi kendali tuannya.
Nah, puasa yang identik dengan lapar adalah untuk menundukkan nafsu. Sebab, seperti yang dikatakan syaikh Said Nursi, nafsu cenderung tidak ingin mengenal Tuhannya. Dia punya kehendak untuk berkuasa dengan sikap keangkuhan yang melampaui batas.
Dari sini pulalah kredo puasa tampil sebagai manifestasi kepekaan rasa terhadap sesama. Kepekaan untuk dapat mengecap kepahitan hidup tetangga-tetangga kita yang kelaparan.
Ramadan momen belanja
Namun demikian, memasuki ramadan animo publik menyeruak bukan hanya dalam lingkup religius. Sebab, eksistensi ramadan di masyarakat kita tak hanya soal agama ansich, melainkan ia membuhul dengan segenap aktivitas budaya dan tradisi secara kohesif yang sulit dilerai batasannya.
Agama yang sifatnya sakral harus membaur dan padu dengan tradisi yang sifatnya profan. Kita akui, memang syariah sebagai trayek penghambaan tak akan pernah lepas dengan pernak pernik budaya yang melingkarinya.
Hanya saja, aspek religius kerap kali terpelanting, kalah bergumul dengan budaya. Sehingga agama hanya sebatas formalitas yang saklek.
Dalam artian, kita melakukan segenap anjuran agama sebatas penguguran tanggung jawab, tanpa perlu menginternalisasi makna-makna esoteris di balik itu.
Belum lagi, saat ini kita memasuki babak baru peradaban. Kehidupan kita kian menelusup ke rimba kapitalisme. Dimana dalam kehidupan kontemporer, uang dan mode menjadi kiblat dan standar nilai moral tertentu.
Kapitalisme sebagai peradaban yang bercirikan uang, spirit produksi yang tak ketulungan melahirkan mental konsumtif.
Disokong iklan-iklan yang bertandang di segala celah media yang ada, ritme budaya konsumtivisme semakin menemukan momentumnya untuk memengaruhi paradigma masyarakat.
Tak pelak lagi, agama dengan segala sakramen, ritualitas dan peribadatannya terdorong secara paksa ke arah sudut, terseduksi menjadi komoditi. Bahkan, na’uzubillah, nilai dan substansi agama ikut tergeser sepenuhnya menjadi sekadar komoditi belaka.
Fenomena ini menjadi toksik dan menjangkiti hampir seluruh umat beragama. Terutama bagi mereka yang sering bersentuhan dengan teknologi dan kemajuan sarana informasi.
Setelah lebih dua belas purnama aktivitas kita betul-betul dikerangkeng akibat wabah, namun dapat kita saksikan gegap gempita ramadhan sesi kedua corona kali ini mengalami perkembangan. Geliat ekonomi di bulan ini mengalami hal yang serupa. Tak seperti ramadhan tahun kemarin dimana aktivitas pasar amat sepi, tahun ini toko-toko, pasar-pasar dan pusat belanja lainnya mulai menampakkan rona pernak-perniknya.
Sekalipun harus mengadopsi dan beradaptasi dengan pola kebiasaan baru, yakni sesuai dengan prokes yang dijalankan pemerintah. Tampaknya, geliat ekonomi yang sempat jungkir balik kini menampakkan rona cukup sumringah. Masyarakat sebagai subjek ekonomi berpacu dalam mengakumulasi besar-besaran.
Menurut, Jusman Dalle Direktur Eksekutif Tali Foundation, praktisi ekonomi digital, yang dilansir detik.com (12 Apr 2021 15:40 WIB) menyebutkan ada energi ganda dalam menghela ekonomi ini. Pertama, optimisme yang bersenyawa dengan gelora spiritual. Kedua, jauh sebelum ini kita sudah mengadopsi digitalisasi dalam rentang setahun pandemi.
Sudah jadi fenomena umum pula bahwa ramadhan merupakan momentum belanja besar-besaran. Tradisi belanja di tubuh masyarakat sudah bersenyawa dengan gelora spiritual mereka.
Mode dan fashion menjadi bagian tak terpisahkan dengan aktivitas sosial masyarakat. Memiliki barang baru dan berharga seperti; baju baru, kendaraan baru, dan seterusnya seolah menjadi prasyarat kebahagiaan dan kemeriahan ramadhan.
Bahkan ada yang terjangkit penyakit shopilimia, yakni penyakit gila belanja. Akibatnya, selama mereka belum mendapatkan barang incarannya, mereka akan berusaha mati-matian untuk mendapatkannya.
Dari sini, visi utama yang dikandung ramadhan menjadi terjungkal. Momen untuk mendorong pola hidup sederhana: makan dan minum apa adanya, menjadi jauh panggang dari api.
Lantas dimanakah puasa yang sejatinya mengontrol nafsu?. Apakah eksistensinya sekadar ritus tanpa makna yang akan berlalu begitu saja?. Jawabannya, mari kita pulang ke diri masing-masing.
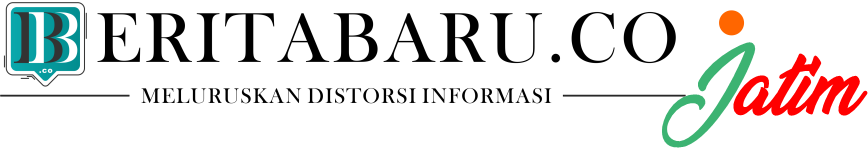
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co






