
Cermin
Perempuan berumur 54 tahun dan sedikit bongkok itu terlihat mondar-mandir di samping jenazah suaminya. Sesekali ia pandangi wajah suaminya yang kaku, duduk di sebelahnya dan menggumam di samping telinga suaminya. Puas menggumam, perempuan paruh baya dengan codet di mukanya itu kembali beranjak dan berputar di dalam rumahnya. Para pelayat tak menghiraukan ulah tuan rumah yang seolah tak menghormati tamunya itu. Sanak saudaranya pun tak acuh dan sibuk menata perlengkapan si mayat, juga para tetangga yang menutup mata melihat ulah tuan rumah dan sibuk berjejal di dapur memotong daging kambing yang cuma dua kilo itu dengan belasan labu untuk menyiapkan seporsi besar gulai guna melepas kepergian si mayat. Hanya anak laki-laki satu-satunya yang menaruh peduli dan selalu mengekor pantat perempuan tua itu. Ya, anak lelakinya yang sudah puluhan tahun bekerja di luar pulau semenjak lulus dari SMA. Menjadi kuli untuk para kontraktor. Dan kali ini harus pulang ke desanya karena bapaknya meninggal. Perempuan tua itu masuk ke kamar dengan gugup.
“Nardi, secepatnya harus kau tutup cermin itu. Jangan biarkan seinci pun mampu memantulkan sinar dari lampu, juga matahari yang masuk lewat celah jendela kamar.”
Perempuan itu memandang cemas anaknya dan berdiri tepat di depan cermin kamarnya sambil membentangkan kedua tangan keriputnya. Melekatkan tubuhnya pada cermin demi menghalau cahaya mengenai cerminnya, serupa seorang ibu yang melindungi anaknya dari binatang buas.
Nardi mengangguk tanpa sedikit pun bertanya dan segera membongkar isi lemari ibunya mencari kain untuk menutup cermin. Diobrak-abriknya lemari dengan satu daun pintu yang mulai tanggal engselnya. Namun, yang ia temukan hanya beberapa kutang lusuh yang mengerut talinya, kaos-kaos serupa ayakan pasir bertuliskan partai yang didapatkan menjelang pemilu, juga sarung dengan bercak darah yang mengering.
“Hanya ini, Mak,” Nardi memberikan sarung itu pada emaknya. Mata tua emaknya yang keriput itu memandang sejenak sarung yang ujungnya menempel darah, membentuk lingkaran yang tak sempurna. Ya, darah yang dulu mengucur dari pipinya yang bercodet itu.
“Jangan yang itu, hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar,” perempuan itu setengah berteriak. Para pelayat yang datang dan menyaksikan ulah perempuan itu pun saling sikut dan menggumam tak jelas. Beberapa yang lain menggeleng sambil mengelus dada.
“Tapi hanya ada ini, Mak,” Nardi melenguh kesal.
Perempuan itu menundukkan wajahnya sejenak dan segera beralih memandang sarung yang membebat badan Nardi.
“Lepas sarungmu!”
Mata perempuan itu menyala.
“Tapi Mak, sarung ini Nardi pakai untuk menyalati mayat bapak nanti,” Nardi memegang kuat sarungnya. Tak hendak melepasnya. Namun, dengan cepat tangan emaknya menyambar dan loloslah sarung itu dari badan Nardi. Dengan sigap perempuan tua itu menutup cermin satu-satunya yang ada di rumahnya. Dikaitkannya ujung-ujung sarung itu pada dinding bambuyang mulai berlubang di sana-sini oleh ulah beringas tikus.
“Pakai sarung bapakmu,” perempuan tua itu berkata dengan nada ditekan.
***
Rumah berukuran 3 x 6 meter beralaskan tanah bergelombang itu semakin sesak dan pengap oleh lalu lalang para pelayat. Bau sedap gulai dari dapur membuat setiap hidung yang membauinya bergerak riang. Sedang perempuan tua itu kembali mendekati mayat suaminya dan berucap pelan, “Pergilah Kang, sudah kumaafkan semuanya. Cermin itu, juga sudah rapat kututup.”
Selesai berkata, perempuan itu menutup kepala suaminya dengan jarikyang bercorak daun siwalan, air mata mengalir melewati pipinya yang cekung dan keriput, juga melewati codet yang belum lama menghuni pipi kirinya. Ia sendiri tidak tahu, apakah itu air mata kesedihan ataukah air mata kebahagiaan. Sedih karena tak ada lagi yang menemaninya mencari kayu bakar untuk dijual ke pasar demi perut yang semakin mengelinting ususnya karena kemiskinan ataukah bahagia karena tak akan ada lagi bekas memar juga sakit di badannya.
Jam menunjukkan pukul 10.00 saat para pelayat mulai menyalati jenazah suami perempuan tua itu dan bersiap memberangkatkannya ke makam desa yang terletak di sebelah hutan jati yang mulai tinggal akarnya. Perempuan itu memandang kuyu keranda suaminya yang diangkat oleh empat orang termasuk anak laki-lakinya. Rombongan pelayat dan pengantar mayat suaminya pun bergerak meninggalkannya dan hilang ditelan jalan yang menikung.
***
Nardi mendekati emaknya yang terduduk bisu di ranjang kamarnya, mata tua emaknya menatap cermin yang kini tak lagi dapat memamerkan wajahnya yang penuh dengan kerutan, semakin banyak garis kerut yang terlihat, menandakan semakin banyak pula kepedihan dan kepiluan yang dilaluinya. Sarung penutup cermin itu kini serupa kain penutup panggung sebelum pertunjukan opera dimulai. Ya, opera kehidupannya yang ia sendiri enggan untuk mengingat dan merasainya kembali.
“Mak capek?” Nardi memijit pundak emaknya yang tak lagi berdaging. Hanya tinggal tulang belulang yang semakin menonjol dan runcing.
“Mak tak lagi dapat merasakan apa pun di tubuh mak ini, Nardi.”
“Kenapa, Mak?”
“Entahlah, sepertinya bapakmu sudah menjadikan emakmu ini mati rasa.”
Perempuan itu berucap dan terus saja memandang sarung yang menutupi cermin di hadapannya. Nardi menelisik pedalaman emaknya, namun tak secuil pun ia mampu menerka. Hatinya terus saja tergelitik untuk menanyakan alasan emaknya melakukan hal yang tak wajar menurutnya, menutup cermin selepas kematian bapaknya. Hal yang tak pernah dilakukan oleh neneknya ataupun mbahbuyutnya. Nardi pun mencoba menghilangkan rasa penasarannya itu dengan bertanya pada emaknya.
“Mak, kenapa cermin itu harus Mak tutup dengan kain sarung?” Nardi beranjak dari duduknya dan coba mengambil sarung penutup cermin itu. Namun emaknya menarik tangan Nardi dan memandangnya tajam.
“Biarkan saja sarung itu tetap pada tempatnya, Nardi. Jangan pernah lagi kau coba membukanya.”
“Tapi kenapa, Mak,” Nardi memandang emaknya yang mulai berubah rona wajahnya. Lama Nardi menunggu jawaban. Dilihatnya perempuan tua itu menghela nafas panjang dan berat, seolah batu besar telah menindih dadanya.
“Cermin itu menyimpan luka yang dalam, Nardi,” mata perempuan itu meredup.
“Luka, Mak?”
“Ya, luka. Cermin itu menyimpan segala kepedihan emakmu selama ini. Setiap kali emak bercermin, di situ emak lihat bapakmu menyiksa tubuh emakmu ini,” air mata perempuan tua itu mengalir dan lagi-lagi melewati codet di pipi kirinya. Terlihat kening Nardi berkerut mendengar jawaban emaknya. Kebingungannya semakin menjadi. Seolah mengerti kebingungan Nardi, emaknya pun kembali berkata.
“Iya, Nardi. Selama ini bapakmu selalu saja menyiksa emak, luka di tangan, punggung, kaki, juga codet di pipi emak ini, semuanya ulah bapakmu, belum lagi luka yang tidak terlihat ini,” perempuan tua itu memegang hatinya.
Kedua alis Nardi bertaut.
“Kenapa emak selama ini tidak cerita sama Nardi?”
“Kamu sudah susah dengan dirimu sendiri, Nardi. Apa pantas emakmu ini menambah berat bebanmu?”
“Tapi Mak, Nardi anak emak. Sudah seharusnya beban emak juga menjadi beban Nardi.”
“Seberat apa pun beban seorang ibu di dunia ini, tak sepatutnya ditumpahkan pada anaknya, Nardi. Begitu juga dengan emakmu ini.”
“Iya Mak, Nardi ngerti. Tapi bagaimana bisa bapak sekejam itu, Mak.”
“Bapakmu dari dulu suka berjudi, dan semakin menjadi saat kamu kerja di Kalimantan, emakmu ini yang jadi sasarannya kalau bapakmu kalah dan tidak ada lagi yang bisa dibuatnya untuk berjudi. Uang yang kamu kirim pun juga habis dibuat judi,” perempuan tua itu membiarkan air mata mengalir dari matanya.
“Dan di sini, di depan cermin itulah bapakmu menyiksa emak. Emak sendiri tidak tahu kenapa bapakmu selalu melakukannya di sini, di depan cermin ini. Mungkin bapakmu ingin emak terus mengingatnya.”
Nardi mengelus rambut putih emaknya, juga dipegangnya tangan emaknya yang tergores memanjang dengan daging yang menyembul keluar. Dirasainya tubuh emaknya kini semakin kurus, seperti papan yang terombang-ambing di lautan lepas. Dibukanya jarik yang menutupi kaki emaknya, dielusnya luka bakar yang memakan kulit luar emaknya. Disingkapnya baju emaknya, dilihatnya punggung emaknya dengan luka yang berbentuk bulat kecil dan menghitam akibat sundutan rokok, juga codet yang ada di muka emaknya dipandanginya dengan iba, luka yang darahnya baru mengering entah berapa hari yang lalu, kain untuk mengelap darah dia biarkan tergeletak di lemari tanpa dicuci. Tak terasa, air mata Nardi meleleh, pundaknya berguncang hebat dan dadanya sesak. Dipeluknya tubuh ringkih emaknya. Pelukan emaknya kini tak dirasainya lagi karena tangan emaknya yang mulai melemah. Hingga tiba-tiba tanah yang mereka injak berguncang hebat. Nardi dan emaknya panik, dengan terhuyung-huyung mereka bangkit dari duduknya. Sekuat tenaga mereka berlari keluar rumah dan beberapa menit kemudian terdengar oleh mereka suara nyaring dari dalam kamar. Suara cermin yang jatuh dan hancur berkeping-keping.
***
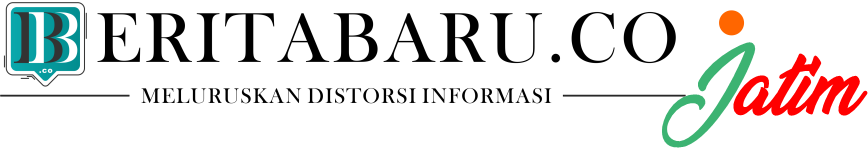
 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co







apa tiba” ada gempa atau semacamnya sehingga ,tanah brgoncang dan membuat cermin tua itupun trjatuh ?